
Halaman Masyarakat Adat | 5 Mei 2024 | Catatan Kusni Sulang: KAPAKAT DAYAK MANGGATANG UTUS
Radar Sampit, Minggu, 5 Mei 2024
“Kamu seharusnya tidak menyerah terhadap apapun yang terjadi padamu. Maksudku, kamu seharusnya menggunakan apa pun yang terjadi padamu sebagai alat untuk naik, bukan turun.” – Bob Marley
“Gagal hanya terjadi jika kita menyerah.” – Bacharuddin Jusuf Habibie
“Aku sudah pernah merasakan semua kepahitan dalam hidup dan yang paling pahit ialah berharap kepada manusia.” – Ali bin Abi Thalib
Catatan Kusni Sulang: KAPAKAT DAYAK MANGGATANG UTUS
Penyunting: Andriani SJ Kusni

Dalam rangka merayakan hari jadinya yang ke-20 pada 14 Mei 2024 mendatang, Koperasi Persekutuan Dayak (KPD) akan menyelenggarakan Seminar Internasional “PAKAT DAYAK” di Ballroom Best Western Batang Garing Hotel, Jalan RTA Milono Km. 1,5 Palangka Raya.
Seminar akan menghadirkan para para narasumber antara lain: Dr. Agustin Teras Narang, S. H. (anggota DPD-RI, mantan Gubernur Kalimantan Tengah); Dr. Ir. Willy M. Yoseph, M.M. (Ikatan Cendekiawan Dayak Nasional [ICDN]); Dr. Ringah Anak Kanyan (Deputy Dean [Industry and Community Engagement] Faculty of Applied and Creative Arts University Malaysia Sarawak [UNIMAS]); Suroto (CEO Induk Koperasi Usaha Rakyat); Stepanus Djuweng (salah seorang penggagas Koperasi Pancur Kasih Pontianak dan Institut Dayakologi Pontianak); B. Rita Sarlawa, S. E., M. Si (Ketua CU Bétang Asi); Ambu Naptamis, S. H., M. H. (salah seorang penanggung jawab utama KPD).
Dalam Kerangka Acuan Keigatan dijelaskan bahwa Seminar Internasional ini mengambil tema “Mandiri secara Ekonomi, Berdaulat secara Politik, Bermartabat secara Budaya” dengan tujuan melakukan “Kilas balik sejarah dan refleksi perjalanan KPD Kalimantan Tengah (Kalteng) dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya sejak berdiri pada 14 Mei 2004 hingga berusia 20 Tahun pada 14 Mei 2024, Meningkatnya wawasan dan pengetahuan para insan Koperasi tentang gerakan Koperasi sebagai alat pemberdayaan dalam membangun kemandirian, kedaulatan, Mendorong kepedulian dan perhatian semua pihak dalam membangun model ekonomi gotong royong yang demokratis, dan Mendorong pemahaman dan kesadaran insan Koperasi maupun banyak pihak akan pentingnya terlibat aktif dalam advokasi yang terorganisir dan sistematis bagi pengembangan, perlindungan dan pemajuan gerakan koperasi”.
Baik judul seminar maupun tujuan yang dirumuskan oleh Kerangka Acuan Kegiatan nampak bahwa KPD melihat permasalahan utama yang dihadapi oleh masyarakat Kalimantan Tengah, cq Dayak, adalah soal marjinalisasi. Soal lain, di tengah derasnya arus marjinalisasi ini, yang termarjinal yaitu masyarakat Dayak, bermasalah dalam soal persatuan (kapakat). Hal ini tertera dalam kalimat Kerangka Acuan yang mengatakan “ruh dari PAKAT DAYAK ini beresonansi kembali dan semakin menguat di jiwa dan raga bagaimana legacy PAKAT DAYAK para pendahulu ini harus terus ditumbuhkan dan diperkuat menjadi suatu kesadaran dan dorongan kolektif”.
“Ruh Pakat Dayak” menurut Kerangka Acuan “intinya mengandung pengertian, kesepakatan, kerukunan, persatuan dan kesatuan langkah dan pandangan pada suatu kurun waktu. PAKAT DAYAK berarti dan berfungsi sebagai kerangka interaksi dan integrasi, mengandung suatu “kebulatan pikiran, pandangan dan langkah ke suatu tujuan” atau “suatu pencerahan pikiran atau kebangkitan”.
Jadi dalam pandangan Kerangka Acuan Seminar, masalah utama masyarakat Dayak Kalteng hari ini adalah ketidakberdayaan alias keterpurukan menyeluruh dan ketidaan kapakat (persatuan) di kalangan Dayak bahkan di beberapa tempat terjadi Dayak mengelahi Dayak baik secara fisik, apalagi politik didasari oleh pandangan “semua pangkalima” dan menggunakan “jadi bari atawa diá” (jadi nasi atau tidak) yang hedonistik sebagai gantang penakar utama.
Semangat merasa diri juga pangkalima sebenarnya sebagai petunjuk adanya kepercayaan diri adalah sesuatu yang baik. Tapi jika semangat ini dipimpin oleh ide egoistik, maka ia akan menyebabkan Dayak tercerai-berai dan Dayak tak segan mengelahi sesama sehingga Dayak mengakibatkan keterpurukan atau marjinalisasi bukannya teratasi tetapi kian menjadi-jadi.
Keterpurukan menyeluruh yang terus berlangsung hingga sekarang, sebenarnya sudah sejak lama diingatkan oleh Raja Putih, nama lain dari James Brooke yang menguasai Sarawak. Pada masa ia menguasai Sarawak, James Brooke (1841-1863) berpesan kepada Orang Dayak: “Kumohon, dengarkanlah kata-kataku ini dan ingatlah baik-baik: Akan tiba saatnya, ketika aku sudah tidak di sini lagi, orang lain akan datang terus-menerus dengan senyum dan kelemah-lembutan, untuk merampas apa yang sesungguhnya hakmu yakni tanah di mana kalian tinggal, sumber penghasilan kalian, dan bahkan makanan yang ada di mulut kalian. Kalian akan kehilangan hak kalian yang turun-temurun, dirampas oleh orang asing dan para spekulan yang pada gilirannya akan menjadi para tuan dan pemilik, sedangkan kalian, hai anak-anak negeri ini, akan disingkirkan dan tidak akan menjadi apapun kecuali menjadi para kuli dan orang buangan di pulau ini.”
Pesan serupa juga sudah disampaikan oleh para pendiri Kalteng dalam kata-kata yang sekarang sudah jadi pengetahuan umum: “Éla sampai témpun pétak batana saré, témpun uyah batawah bélai, témpun kajang bisa puat” (jangan sampai punya tanah berladang di tepi, punya garam hambar di rasa, punya atap basah muatan—Penulis). Karena itu, umumnya Orang-Orang Dayak pun paham jalan keluarnya adalah Jalan Manggatang Utus.
“Manggatang Utus” (Manggatang=Mengangkat; Utus=Suku, Daerah, Bangsa) hari ini merupakan ungkapan dan menjadi slogan umum di kalangan masyarakat Dayak Kalteng. Manggatang artinya posisi seseorang, etnik dan atau bangsa berada di tingkat bawah. Bahkan di beberapa daerah Dayak, posisi ini digambarkan sebagai ‘batang tarandam’ (batang pohon kayu yang mudah ditebang dan terendam, berada dalam air). Karena itu di daerah ini, ungkapan dan slogannya menjadi “Mengangkat Batang Terendam Hingga Kembali Berdaun dan Berbunga’.
Baik “Manggatang Utus” maupun “Mengangkat Batang Terendam” atau “gerobak tua masuk kubangan lumpur” maknanya serupa yaitu berada dalam keadaan terpuruk. Termarjinalisasi secara menyeluruh di kampung-halaman mereka sendiri. Kalteng tidak lagi menjadi “Provinsi Dayak” sebagaimana dikatakan oleh alm. Profesor Mubyarto seusai melakukan penelitian di daerah perdesaan Kalteng. Namun, “Manggatang Utus” adalah ungkapan dari suatu konsep umum. Bagaimana konkretnya cara “Manggatang Utus”, sampai hari ini belum ada kesatuan pandangan. Barangkali, menyatukan pandangan bagaimana “Manggatang Utus” merupakan pertanyaan mendesak yang perlu dijawab oleh Orang Dayak. Oleh karena keadaan terpuruk sudah menjadi pengetahuan umum seperti halnya dengan ide “Manggatang Utus” tanpa ada bantahan, semua sepakat, pertanyaan saya: Mengapa tidak ide “Manggatang Utus” atau “Mengangkat Batang Terendam Hingga Kembali Berdaun dan Berbunga’ diangkat ke tingkat ideologi bersama. Ide pemersatu para “pangkalima”?
Mengapa saya sebut ideologi atau adicita?
Kata Ideologi pertama kali diperkenalkan oleh filsuf Prancis Destutt de Tracy pada tahun 1796. Kata ini berasal dari bahasa Prancis idéologie, merupakan gabungan 2 kata yaitu, idéo yang mengacu kepada gagasan dan logie yang mengacu kepada logos, kata dalam bahasa Yunani untuk menjelaskan logika dan rasio. Destutt de Tracy menggunakan kata ini dalam pengertian etimologinya sebagai “ilmu yang meliputi kajian tentang asal usul dan hakikat ide atau gagasan”.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ideologi atau adicita merupakan kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat (kejadian) yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Ideologi berarti a system of ideas, akan mensistematisasikan seluruh pemikiran mengenai kehidupan ini dan melengkapinya dengan sarana serta kebijakan dan strategi dengan tujuan menyesuaikan keadaan nyata dengan nilai-nilai yang terkandung dalam filsafat yang menjadi induknya. Artinya untuk mencapai tujuan, adicita memberikan juga strategi, taktik dan program yang jelas.
Orang Dayak yang tergabung dalam organisasi atau partai politik apa pun dan mana pun, seniscayanya menjunjung adicita ini sebagai adicita bersama yang mempersatukan. Karena marjinalisasi bersifat menyeluruh maka penanganannya pun tidak bisa tidak harus menyeluruh pula.
Dayak yang berada turut dalam penyelenggaraan Negara, niscaya berjuang melalui penyelengaraan Negara agar Utus Tagatang, Batang Terendam Terangkat, gerobak tua keluar dari kubangan lumpur tanpa mengalami kerusakan. Yang bekerja di bidang hukum, bagaimana menelurkan regulasi-regulasi yang berpihak pada masyarakat Dayak atau rakyat. Yang di bidang pendidikan, bagaimana bisa melahirkan barisan sumber daya manusia Dayak yang berdaya dan berkualitas, bukan menjadikan dunia pendidikan sebagai barang dagangan. Yang bergerak di bidang ekonomi, bagaimana membuat masyarakat Dayak kuat dan berkembang di bidang ekonomi. Yang bekerja di bidang sastra-seni dan media massa, bagaimana menumbuhkembangkan kesadaran dan keyakinan untuk menjadi “kapten atas hidupnya sendiri” sebagai anak manusia melalui bidang estetika dan informasi. Semua bidang bekerja ke arah “Mengangkat Batang Terendam” dan “Manggatang Utus”. Oleh sebab itu, gagasan Manggatang Utus atau Mengangkat Batang Terendam juga berfungsi sebagai metodologi.
Selain sebagai ideologi dan metodologi, “Manggatang Utus” dan atau “Mengangkat Batang Terendam” adalah nama dari suatu gerakan. Gerakan adalah suatu usaha massal bersama, terorganisasi dan terencana atau terprogram, untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. Dalam hal ini, “Manggatang Utus”.
Hal penting dalam Gerakan Manggatang Utus ini adalah sifat independen.
Jangan sampai menjadi kuda kepentingan politik dan ekonomi sementara pihak yang membuat Gerakan akan terjegal di tengah jalan. Karena itu, basis sosial Gerakan harus bertumpu pada lapisan masyarakat akar rumput baik di daerah urban atau pun di daerah perdesaan. Untuk demikian, maka pendidikan penyadaran merupakan kegiatan terus-menerus berbarengan dengan kegiatan-kegiatan di sektor-sektor lain. Kegiatan-kegiatan di semua sektor seniscayanya tidak meninggalkan atau mengabaikan masalah pendidikan ini, tidak sebatas pada permasalahan teknis sektoral. Gerakan dilakukan oleh, dari dan untuk manusia. Kuat tidaknya Gerakan Manggatang Utus yang hakikatnya tidak lain dari Gerakan Pemberdayaan, tidak terpisahkan dari tingkat kualitas para peserta Gerakan. Keberlanjutan Gerakan juga tidak terpisahkan dari pendidikan massa Gerakan. Dengan tingkat kesadaran tentang adicita Manggatang Utus, Gerakan akan mungkin berkembang seperti yang disebut oleh Bung Karno, “self propelling growth”, tumbuh membesar dan membesar seperti bola salju.
Manggatang Utus adalah suatu adicita. Adicita adalah sari kebudayaan, sebagaimana ditunjukkan oleh gambar berikut:

Dari gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa, sistem budaya digambarkan dengan lingkaran yang paling dalam dan merupakan inti, kemudian sistem sosial digambarkan dengan lingkaran kedua di sekitar inti, sedangkan kebudayaan fisik digambarkan dengan lingkaran yang paling luar.
Jika mengutip Talib Muhammad-Bin- Salman Zardari Arsif dari Studi di Center for Talented Youth (CTY), ideologi dan budaya berkaitan erat karena ideologi membentuk budaya dan budaya memperkuat ideologi. Ideologi mengacu pada seperangkat keyakinan, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip yang memandu perilaku dan keputusan individu atau kelompok. Budaya, di sisi lain, mencakup keyakinan, nilai, adat istiadat, praktik, dan artefak bersama yang menjadi ciri suatu masyarakat atau kelompok. Masih merujuk pada Talib: ”Ideologi mempengaruhi budaya dengan membentuk keyakinan dan sikap masyarakat terhadap berbagai isu, seperti politik, agama, norma sosial, dan moralitas. Misalnya, ideologi politik seseorang dapat memengaruhi pandangannya terhadap isu-isu seperti imigrasi, layanan kesehatan, atau pengendalian senjata, yang pada gilirannya memengaruhi norma dan praktik budaya dalam masyarakatnya”.
Demikian pula, budaya memperkuat ideologi dengan melanggengkan keyakinan dan praktik tertentu yang penting bagi ideologi suatu kelompok. Misalnya, masyarakat yang menghargai individualisme, kemungkinan besar akan mendorong praktik-praktik seperti kewirausahaan dan kemandirian, yang memperkuat ideologi individualisme.
Secara keseluruhan, ideologi dan budaya saling bergantung karena perubahan di satu sisi dapat menyebabkan perubahan di sisi lain (https://www-quora-com.translate.goog/How-is-ideology-related-to-culture?).
Gerakan Manggatang Utus bukanlah gerakan etnosentrisme sebab Gerakan ini tidak akan berhasil jika mengambil sikap tutup-pintuisme dan ekslusif. Sejarah sosial-politik dan kebudayaan Dayak mengatakan bahwa kebudayaan Dayak itu bersifat inklusif. Bahkan kebudayaan mana pun, saya kira, intinya selalu inklusif. Dalam kondisi Kalteng seperti hari ini, kembali pendidikan penyadaran yang berkelanjutan tetap memainkan peranan utama, bukan hanya pada Orang Dayak, tetapi juga untuk semua Uluh Kalteng (Orang Kalteng).
Manggatang Utus hanya mungkin terwujud dengan adanya kapakat, pertama-tama kapakat Dayak.***

Halaman Budaya Sahewan Panarung | 28 April 2024 | Cerpen Swary Utami Dewi: SENGKARUT LÉWU
Radar Sampit, Minggu, 28 April 2024


“Jika saja mereka tidak datang, tidak akan ada persilangan kata di léwu ini. Ah, apakah nanti yang terjadi selanjutnya?”
Aku menghela nafas. Masih terbayang dibenakku hiruk-pikuk pertemuan di aula Huma Bétang Jumat kemarin. Ketika itu, suara yang tidak setuju beradu tinggi dengan yang setuju. Mantir Adat léwu, Bungan Juru, yang biasanya selalu didengar petuahnya, kali ini seolah tidak berdaya. Dia terlihat berkali-kali menghela nafas dan menggelengkan kepala. Pesona aura di sekitar tubuhnya seakan berhenti berpendar. Pudar meredup saat itu.
Umai menggawilku. Membuyarkan tatapan bingungku terhadap apa yang terjadi di pertemuan, yang berlangsung sejak pagi di Jumat itu.
“Siwa, segera ambil kopi untuk Bué’.” Perintah ibuku tegas, membuatku tidak jadi mengatakan ‘sebentar’.
“Léha éwén tuh… bahali tutu ampi” (mengapa ya mereka… tampaknya sangat susah kali ini).
Perkataan singkat itu yang sempat kudengar, saat aku memberikan segelas kopi untuk Bué’-ku. Aku seolah merasakan resah gelisah degup jantung tetua adat kampung kami ini. Seolah aku merasakan riak tak beraturan dari syaraf-syaraf di kepala kakekku ini. Aku lalu beringsut menjauh. Duduk di pojok rumah adat luas itu.
Sabtu ini, buku sketsa kembali kubuka. Kulukis garis-garis gelisah di pertemuan kampung kemarin. Kugambar jerit protes Mina Lési yang menyatakan ketidaksetujuannya jika sebagian dari tanah adat peninggalan leluhur berpindah tangan. Telunjuk tanteku ini, yang mengarah ke Mang Punding, kulukis tegas. Kurangkai dalam goresan sketsa apa pun yang kusaksikan pada Jumat itu.
Semua berjejal padat di buku ini. Lembar demi lembar. Hampir penuh sesak hingga hanya menyisakan dua halaman di belakang. Entah sudah berapa kali pula kuraut pensil 2B ini, supaya sketsa yang kuhasilkan bisa terus terukir nyata.
Saat aku membalik dua halaman terakhir, Turiana tiba-tiba datang memberikan dua buku sketsa kosong.
“Capek, Kak. Sudah berkeliling lima toko, baru dapat.” Dia mengeluh. Mukanya terlihat merah. Bau keringat adikku yang lepas bermandi matahari itu sempat tercium. Aku bisa membayangkan usaha keras bocah kelas enam sekolah dasar ini menggenjot sepeda tua milik Bué’ untuk mencari buku sketsa sampai ke ibukota kabupaten, di saat hari sedang terik.
Aku bergegas ke dapur mencari apa yang ada di meja. Kénta… aha… Lantas kubawakan semangkuk kénta lezat dan menyodorinya ke Turiana, yang masih tampak ngos-ngosan.
Sedetik kemudian matanya berbinar. Dia berhenti mengeluh. Adikku melahap habis makanan dari beras ketan sangrai tersebut. Lalu dia mengambil kendi berisi air putih dari meja dan menuangkan air putih itu ke gelas, lagi dan lagi. Glek … glek … glek.
Aku lanjut mengukir sketsa di lembar belakang. Aku berniat meneruskannya di buku sketsa yang baru dibeli Turiana, jika dua lembar terakhir sudah terisi penuh.
Ya… Buku sketsa inilah yang sekarang sedang kupenuhi dengan resah gelisahku. Saat senja kemarin menghampiri, pakat léwu tak jua ada. Maka Bué’-ku, Sang Mantir Adat, Bungan Juru, menghentikan pertemuan dan memutuskan akan ada pertemuan lanjutan dua hari kemudian, pada hari Minggu. Kulihat dia saat itu lagi-lagi tertegun. Bué’ menghabiskan malamnya tanpa banyak cakap. Malam yang muram. Langit yang tak berbintang seolah berempati pada kemuraman lelaki tua itu.
***
“Pagi besok Punding katanya akan datang lagi memperlihatkan usulan perjanjian yang sudah ditawarkan si bos sawit. Katanya, yang ditawarkan lebih banyak lagi. Bahkan mungkin, si bos akan datang langsung.” Mina Dadang berujar.
“Tak kan kubiarkan Punding memengaruhi seisi léwu ini.” Mina Dadang melanjutkan ucapannya. Kali ini lebih berapi-api. Semburan geramnya jelas terwujud dalam setiap kalimat.
Aku tidak jadi beranjak dari dapur. Rasa ingin tahuku menguat saat mereka berbicara tentang Mang Punding, salah satu sepupu laki-laki Umai. Mang Punding memang sosok yang menarik bagiku. Menarik karena dia punya rumah lain di luar kampung. Menarik karena selama beberapa tahun terakhir, dia berhasil bekerja di kota yang jaraknya harus ditempuh lima jam dari kampung. Dan makin membuatku ingin tahu karena minggu lalu saat dia datang lagi ke léwu, Mang Punding sudah mengendarai mobil kap terbuka bersama beberapa orang. Tentu saja uluh léwu ternganga melihat gaya tampilannya yang amat jauh berbeda.
Pertukaran kata Umai dengan Mina Dadang tentang sepupu laki-laki mereka ini tentu bisa memperkaya sketsaku. Mendadak pikiran isengku muncul. Cecak di atas tiba-tiba memukul ekornya— menimbulkan bunyi kecil yang membuatku mencari tahu dari mana tepatnya arah bunyi itu. Cecak ini paham maksudku ternyata. Aku tersenyum menyeringai dan menengadah melihat ke cecak nakal itu. Ia seakan membalas dengan kembali memukul ekornya beberapa kali.
“Dikiranya kita tidak paham bahwa Punding sudah dibayar besar untuk mau jadi cecuruk biadab bos sawit itu. Mau dari Jakarta, mau dari mana … aku tidak peduli. Aku tidak pernah mau menerima kubur moyangku dipindah. Haram bagiku membiarkan himba-ku dijarah. Pantang bagiku adat dipinggirkan demi uang dan fasilitas ini itu.”
Sepupu perempuan Umai-ku ini terus menerus menumpahkan amarahnya. Sementara Umai masih terus melanjutkan kegiatannya menggerus bawang merah, tomat dan cabai yang sebelumnya sudah ditumis dengan minyak kelapa. Aku tahu sambal tomat Umai pasti akan sedap luar biasa. Seperti sebelumnya dan sebelumnya.
“Hei… Kambang. Tidakkah kau ingin berkomentar? Sedikit saja …” Ucapan tinggi Mina Dadang tetap tidak membuat Umai berhenti mengolah sambal.
“Kurasa kau sudah tahu ketidaksetujuanku sejak awal. Sejak Punding mengajak kita berunding di rumah almarhum Tambi Buyut dua minggu lalu,” jawab Umai ringan, hampir tanpa ekspresi. Tangannya mengambil piring kecil sebagai wadah sambal lezat itu.
“Janji-janji yang dibawa oleh bos sawit melalui Punding memang bisa membuat geger lewu. Siapa yang tidak tergoda dengan janji adanya sekolah di kampung, jalan beraspal, listrik ada kapan saja, sumur air. Apalagi itu … Pekerjaan tetap di perusahaan sawit.”
Satu persatu Mina Dadang menguak daya ingatnya tentang janji bos sawit yang dibacakan Mang Punding di pertemuan lewu kemarin.
Aku bergegas menuang semua ucapan Mina Dadang di sketsa. Tampak ada sekolah, tiang listrik, jalan, kampung, Huma Bétang, dan akhirnya hamparan luas: sawit … sawit … dan sawit …
Aku mendadak mengernyitkan dahi. Di mana himba? Di mana kebun tepaken dan kasturi? Di mana pohon-pohon besar tempat berulirnya rotan? Di mana pohon-pohon kapuk kokoh tempat bergantungnya sarang lebah liar? Di mana burung tingang akan bermukim? Di mana tempat suci himba? Bagaimana nasib sungai tempatku dan adikku bermain saat gosong datang? Aku makin nanar melihat sketsa masa depan léwu-ku.
Tepukan di pundak membuyarkanku. Aku gelagapan dan menoleh ke arah Umai yang tampak bingung melihatku. Turiana mendadak masuk bergelayut manja di lengan Umai, seraya meminta air peras tebu. Lalu dia duduk di dekatku.
“Itu apa, Kak?” Dia menoleh lekat-lekat ke sketsa di depanku.
“PR Kakak, ya? Kapan gambarnya harus dikumpul? Kakak dari kemarin gambarnya penuh. Apa semua akan dikumpul? Anak SMA banyak ya tugasnya?”
Turiana bertanya terus sambil meminum air tebu yang diberikan Umai.
Aku tetap diam. Beberapa saat kemudian aku membisikkan sesuatu di telinganya, yang membuat Turiana mengangguk cepat.
“Hei, mau ke mana kalian? Makan dulu!” Umai mendelik melihat aku dan adikku bangkit bersama dari tempat duduk.
“Aku mau beli gula yang tadi Umai pesan. Untuk pertemuan besokkan, Mai?”
Umai memberikan sejumlah uang seraya berpesan agar aku dan adikku cepat kembali untuk makan siang.
Sepeda kesayanganku yang setia menemaniku ke sekolah setiap hari kembali kugenjot. Hanya Jumat kemarin dia tidak kunaiki karena aku membantu pertemuan di Huma Bétang. Turiana terdengar menyanyi kecil di boncengan. Aku mempercepat laju sepeda ke warung terdekat membeli beberapa bungkus gula pasir sebelum kemudian aku sedikit berputar menuju tepi himba.
Sekitar setengah jam aku mengayuh sebelum kemudian tiba di pinggir himba itu. Dan betul… masih ada di sana. Dua mobil besar bercakar tunggal berwarna kuning masih di situ. Aku hendak mencari buah-buahan jatuh minggu kemarin, saat aku melihat ada dua mobil itu. Tinggi menjulang dengan cakar angkuh yang tampak siap menerjang apa pun yang ditujunya.
Aku sempat mencuri dengar percakapan Mang Punding dengan beberapa kawannya yang hadir di pertemuan léwu kemarin bahwa excavator itu akan langsung bekerja mencabut pohon, meratakan tanah dan membabat apa saja saat uluh lewu sudah sepakat. Dan Mang Punding meyakinkan mereka bahwa dia pasti berhasil.
Dan kini, aku dan adikku berdiri tepat di hadapan dua motor mesin ini. Mereka tampak begitu angkuh menjulang tinggi. Aku memandang keduanya lekat-lekat. Mereka-reka apa yang bisa dilakukan dua mesin ini terhadap kampung kami. Apa yang kemudian terjadi dengan himba, tepaken, burung tingang dan semua … dan semua.
Turiana terlihat masih ternganga. Entah bingung atau terpesona. Aku menjawilnya. Berdua kami berjalan mengelilingi dua alat besar ini. Dan ternyata di balik dua mesin angkuh itu ada mobil kap, yang minggu lalu dinaiki Mang Punding dan tiga kawannya.
Aku bergegas mendekati mobil kap itu karena melihat ad tong-tong besar di belakangnya. Bagian belakang mobil ternyata tidak lagi kosong. Setidaknya ada empat tong besar mengisi kap mobil hitam ini.
“Isinya apa ya, Kak?’ Turiana menaiki mobil itu dan sesaat menjerit. “Ini seperti bensin, Kak. Eh bukan…”
Aku ikut naik. Mmm… bisa jadi solar atau sejenisnya untuk bahan bakar mobil. Aku menciumnya lagi. Tapi, mobil manakah yang memerlukan bahan bakar begitu banyak?
Aku teringat sesuatu. Teringat cerita kawanku dari kampung sebelah. Aku berkata perlahan ke Turiana, hampir setengah berbisik. Dan kembali dia ternganga, lalu sesaat kemudian mengangguk.
***
Minggu … Pagi ini orang-orang kembali berkumpul. Sebenarnya bukan orang lain, karena rata-rata masih bersaudara dari satu keluarga besar. Aku hafal satu persatu namanya dan rumahnya karena kami biasa bertemu. Léwu kami memang tidak besar kecuali himba yang masih terbentang luas dan sungai jernih yang tergolong cukup lebar dan panjang.
Tampak Mang Punding dan ketiga kawannya sudah datang menunggu di bagian tengah Huma Betang. Tapi siapa lagi yang ditunggu, ya?
Tidak sampai setengah jam datanglah dua mobil. Bagus dan mengkilap. Beberapa uluh léwu segera melongok. Lalu turun beberapa orang dari mobil.
Aku ternganga memperhatikan mereka. Pakaiannya wah … Rapi. Gaya berjalannya berbeda. Dagu agak naik. Terutama yang berbaju biru. Gagah dan paling menjadi pusat perhatian.
Bué’ menghampiri menyambut tamu-tamu itu. Mang Punding juga turut menghampiri. Tampak pamanku ini menunjukkan rasa hormat berlebih terhadap bapak berbaju biru itu.
“Si bos besarnya datang.” Mina Lési berkata perlahan, namun tegas. Umai dan Mina Dadang yang duduk di dekatnya turut memperhatikan lekat-lekat.
Para tamu kemudian ikut duduk berkeliling di rumah besar, bersama para tetua, perempuan dan laki-laki. Aku harus beringsut ke pojok ruangan, sementara dua mina dan ibuku tetap ada di lingkaran. Tiga singa betina ini kupastikan kembali siap bertarung untuk mempertahankan léwu.
Bué’ memulai acara dengan melakukan tampung tawar kepada para tamu. Mulutnya berkomat-kamit membacakan doa. Aku yakin Bué’ sedang mendoakan yang baik-baik bagi seluruh kampung kami.
Acara baru dimulai dengan petatah-petitih dari para tetua dan tokoh kampung. Lalu kini giliran si bos besar berbaju biru berbicara. Bahasanya tertata. Tangannya ikut bergerak seirama ucapannya. Khas orang berpendidikan kota.
Saat dia masih berbicara tentang keuntungan sawit bagi léwu, tiba-tiba seseorang yang belum dikenal masuk menerobos naik ke Huma Bétang. Nampak terengah dan pucat, dia langsung mendekati Mang Punding dan berbisik. Tepat saat itu, sang bos selesai berbicara.
Mang Punding berbisik ke Bué’ dan dia kemudian berdiri dengan tampang geram.
“Siapa yang berani kurang ajar? Siapa??? Siapa yang berani mencampurkan gula dan butiran pasir ke solar excavator … Siapa yang berani melakukannya? Mesin rusak … rusak …”
Mang Punding terus menerus berteriak marah. Tiba-tiba tubuhnya bergetar hebat. Tak lama dia jatuh berkelonjot setengah kesurupan.
Muka bos sawit yang semula ramah menawan, mendadak pucat, lalu terbelalak. Bué’ ternganga. Yang lain melongo.
Turiana beringsut perlahan bersembunyi di belakang punggungku, lalu mengintip ke arah lingkaran duduk para tamu.
Sementara aku kembali meneruskan sketsaku, di bawah hujanan tatapan tajam dari ibuku dan Mina Dadang.***
Catatan: Versi berbeda dari cerpen ini telah dimuat di satu antologi yang dikurasi oleh Eka Budianta. Cerpen ini kembali dipertajam dan diedit.
Catatan Belakang:
Bue’ merupakan panggilan untuk kakek dalam bahasa Dayak Ngaju.
Gosong di Kalimantan Tengah, umumnya mengacu pada kumpulan pasir yang mengendap dan menjadi daratan sementara di sungai. Letaknya bisa di pinggir atau di tengah sungai. Umumnya, fenomena ini banyak terjadi pada musim kemarau.
Himba artinya hutan. Himba bagi suku Dayak memiliki makna sangat vital. Himba merupakan tempat mencari dan mengambil hasil hutan tertentu, misalnya rotan, madu dan buah-buahan (tepaken, kasturi, durian, lengkeng, langsat, manggis dan sebagainya). Himba juga tempat bercocok tanam dan berkebun, berburu serta tempat bermukimnya berbagai jenis satwa. Himba memiliki fungsi ekonomi, ekologi, spiritual dan sosial budaya bagi suku Dayak. Beberapa bagian himba terlarang untuk dimasuki atau ada ritual tertentu sebelum memasuki lokasi tersebut, karena dipercaya ada kekuatan spiritual yang harus dihormati di tempat itu.
Huma Betang adalah rumah besar adat khas Dayak, terutama di Kalimantan Tengah.
Kasturi merupakan buah endemik di Kalimantan Tengah dan sekitarnya. Bentuknya seperti mangga sebesar genggaman tangan anak kecil. Rasanya manis. Teksturnya berserat. Wanginya agak kuat menyengat.
Kenta adalah kudapan yang terbuat dari beras ketan yang disangrai. Sebelumnya beras ketan itu ditumbuk sampai gepeng di lesung. Lalu direndam sekitar satu jam, kemudian disangrai di atas api kayu bakar. Sesudah dirasa cukup matang, beras ketan gepeng itu dicampur parutan kelapa dan gula. Lalu siap untuk dimakan.
Lewu adalah kampung atau desa dalam bahasa Dayak Ngaju.
Mang adalah kependekan dari Amang. Artinya paman atau om. Terkadang paman juga disebut mamak dalam bahasa Dayak Ngaju.
Mantir adalah tetua adat kampung di desa-desa adat Dayak.
Mina adalah panggilan untuk tante atau bibi dalam bahasa Dayak Ngaju.
Tambi Buyut adalah nenek buyut. Ibu dari kakek atau nenek.
Tampung tawar adalah salah satu ritual adat Dayak Ngaju yang penting. Ritual ini bisa bermakna banyak tergantung konteksnya. Salah satunya untuk tujuan bersyukur, menolak bala atau mengharapkan keselamatan. Dalam penyambutan tamu juga kerap dilakukan tampung tawar. Untuk ritual ini disediakan bahan-bahan tertentu, yakni air yang dicampur wewangian, juga potongan pandan sebagai alat pemercik. Tampung tawar dilakukan dengan memercikkan air tersebut ke kepala, pundak, telapak tangan, lutut dan kaki, dengan menggunakan potongan pandan tersebut. Terkadang ritual ini juga disertai dengan meletakkan butiran beras di atas kepala yang bersangkutan. Beras tersebut sebelumnya diletakkan di suatu wadah. Dalam wadah tersebut, selain ada beras, juga diisi dengan telur ayam kampung mentah.
Tepaken adalah buah endemik di wilayah Kalimantan Tengah dan sekitarnya. Bentuknya serupa durian. Namun warna, rasa dan baunya jauh berbeda. Aroma tepaken tidak kuat menyengat seperti durian. Warna daging buah tepaken kuning keemasan. Rasanya manis.
Tingang adalah nama Dayak Ngaju untuk sejenis burung enggang yang endemik di Kalimantan.
Uluh lewu artinya orang desa atau orang kampung.
Umai adalah panggilan ibu dalam bahasa Dayak Ngaju.

Halaman Masyarakat Adat | 21 April 2024 | MENGAPA KOPERASI PERSEKUTUAN DAYAK (KPD) DIDIRIKAN?
Radar Sampit, Minggu, 21 April 2024
“Dasar kekeluargaan itulah dasar hubungan istimewa pada koperasi. Di sini tidak ada majikan dan buruh, melainkan usaha bersama di antara mereka yang sama kepentingan dan tujuannya.” – Dr. Moh. Hatta
“Koperasi juga bisa mendidik toleransi dan rasa tanggung jawab bersama. Dengan demikian, koperasi bisa mendidik dan memperkuat demokrasi sebagai cita-cita bangsa.” – Dr. Moh. Hatta

Wawancara Radar Sampit dengan Ketua KPD Ambu Naptamis
Pada 14 Mei 2024 mendatang, Koperasi Persekutuan Dayak (KPD) berusia tepat 20 tahun. Berdirinya KPD selain menjawab secara konkret bagaimana keluar dari keterpurukan ekonomi dalam masyarakat Dayak dengan bersandar pada kekuatan-kekuatan yang ada dalam masyarakat itu sendiri, menciptakan lapangan secara berprakarsa, upaya ini sekaligus menjawab keraguan dan pertanyaan: Apa betul Orang Dayak tidak bisa berbisnis?
Selama 20 tahun berkoperasi, generasi muda Dayak pemimpi dan petarung sebagaimana mestinya seorang Dayak, di Palangka Raya, telah mendirikan tiga koperasi toko serba ada dan sekaligus sebagai sekolah berkoperasi.
Untuk mendalami lebih jauh, Radar Sampit menjumpai Ambu Naptamis, S. H., M. H., orang pertama KPD dan salah seorang orang tokoh kunci Credit Union (CU) Bétang Asi, Kalimantan Tengah.
Berikut adalah percakapan singkat tersebut yang diselenggarakan di tengah-tengah kesibukan Ambu menyiapkan acara ulang tahun ke-20 KPD dengan berbagai macam kegiatan. Atas kesediaan Ambu menjawab pertanyaan-pertanyaan kami, Radar Sampit mengucapkan terima kasih.
Radar Sampit (RS): Apa KPD itu? Mengapa didirikan?
Ambu Naptamis (AN): KPD adalah sebuah entitas Koperasi, entitas yang didirikan oleh kelompok masyarakat, komunitas Dayak untuk mengorganisir kepentingan/kebutuhan yang sama, kebutuhan untuk mengembangkan usaha dan mengorganisir komunitas.
RS: Berbentuk koperasi atau PT? Mengapa memilih bentuk itu?
AN: Memilih koperasi karena mengembangkan konsep ekonomi gotong-royong dan mengembangkan dan memelihara nilai-nilai demokrasi dalam menjalankan organisasi dan prinsip gotong-royong ini membuka ruang untuk ekonomi berbagi. Konsep atau sistem koperasi mendorong dan membangun rasa memiliki yang tinggi, kemandirian serta mendorong anggota semua aktif untuk bekerja dalam organisasinya, koperasinya! Di samping kemandirian, yang dibangun dan dikembangkan dalam koperasi juga semangat solidaritas. Salah satu wujud solidaritas dalam koperasi adalah partisipasi anggota dalam bentuk transaksi maupun aktif dalam kegiatan-kegiatan koperasi.
RS: Berapa tenaga kerja yang berhasil direkrut KPD sampai hari ini?
AN: 80 orang karyawan.
RS: Kesulitan-kesulitan apa yang dihadapi dalam mendirikan dan mengembangkan KPD?
AN: Kesulitan-kesulitan yang dihadapi, diantaranya dalam mempersiapkan sumber daya yang menguasai hal-hal teknis dalam tata kelola organisasi/bisnis, membangun jaringan usaha, persaingan bisnis khususnya usaha disektor ritel. Sejak digagas, keberadaan KPD Kalteng didedikasikan untuk melakukan kegiatan/aktivitas pemberdayaan khususnya kepada anggota, ketika anggota berdaya diharapkan berdampak baik kepada peningkatan kesejahteraan komunitas di sekitar anggota tersebut, kemudian melalui lembaga/entitas koperasi memiliki kewajiban untuk memperhatikan pengembangan masyarakat di sekitarnya.***
Ambu Naptamis dan Literasi Finansial Dayak Kalteng Melalui Credit Union
Oleh: Damianus Siyok | Penyunting: Andriani SJ Kusni

Ambu Naptamis adalah salah seorang pejuang ‘Keberdayaan Orang Dayak’ melalui Gerakan Credit Union dan Pemberdayaan Masyarakat.
Sebelum tahun 2000, orang-orang Dayak di daerah (Kalimantan Tengah, khususnya Palangka Raya, Katingan, Gunung Mas, Kapuas, Kotawaringin Timur) tidak memiliki wadah untuk mengelola uang, mendapatkan pendidikan keuangan, dan strategi menyiapkan masa depan keluarga. Mungkin saat itu bisa dikatakan sebagai masa kekelaman ‘dalam konteks strategi pemberdayaan ekonomi’ bagi Orang Dayak.
Lembaga Dayak Panarung
Kondisi ini perlahan-lahan mulai berubah semenjak tahun 2003, ketika Ambu dan rekan-rekan aktivis (Ethos, Cony, Adang, Sepmi, Anse) di Lembaga Dayak Panarung mengorganisir para tokoh dan aktivis lain untuk mewujudkan adanya ‘alat pemberdayaan bagi Orang Dayak’.
CU hadir dan orang Dayak perlahan-lahan memiliki jembatan. Saat ini, warga dari kampung pun bisa menyekolahkan anak-anaknya sampai ke tingkatan pascasarjana, bisa membuat rumah dengan layak seperti halnya orang-orang kota, bisa membeli kendaraan dan bisa berbisnis, bisa ziarah ke Israel atau naik haji dengan perencanaan yang baik.
Masyarakat yang tidak pernah mengenal buku tabungan, kini memegang buku tabungan, yang tidak mengenal istilah ‘investasi’, kini terbiasa dan melakukan investasi.
Penggerak Kemajuan Dayak
Setelah CU hadir di tengah-tengah masyarakat, bahkan abang tukang becak di Pujon bisa menabung lebih dari 100 juta rupiah di CU karena mendapat motivasi yang tidak biasa melalui Pendidikan Motivasi dan Pendidikan CU.
Dan, Ambu Naptamis bisa dikatakan salah satu penggerak, yang menjadikan ‘masa kekelaman ini berubah ke sebuah dunia baru, yang disebut masa kemajuan.’
Di samping menjadi penggerak gerakan CU, Ambu dan rekan-rekannya adalah penggerak ‘Keberdayaan Masyarakat Adat Dayak Kalimantan Tengah’ dengan membentuk Aliansi Masyarakat Adat Kalimantan Tengah. Dan bersama-sama dengan para rekan aktivis seperjuangan, gerakan yang dimotori Ambu membuktikan bahwa Orang Dayak bisa masuk ke bisnis retail dengan mendirikan KPD Swalayan, melakukan advokasi dan pemberdayaan sampai ke kampung-kampung di perhuluan sungai, dengan harapan Orang Dayak memiliki kesadaran dan kepercayaan diri, sehingga tergerak untuk berdaya sejajar dengan masyarakat lain. Teman-teman, ini bahasa saya secara pribadi yang mengenal sosok Ambu Naptamis serta perjuangan beliau bersama rekan-rekan aktivis.
Rekan-rekan yang berjuang itu (bersama dengan Ambu), saat ini bisa dikatakan golongan cukup berada. Kemana-mana naik mobil, bisa menggunakan fasilitas yang di atas orang-orang kebanyakan, situasi yang berbeda dengan tahun 2005 ke bawah.
Ada banyak rekan pelaku yang berjuang bersama beliau. Di mana gerakan itu dimulai tanpa modal, dimulai dengan sepeda motor (bahkan ada yang jalan kaki), naik perahu, naik getek/perahu bermesin dan menembus sungai-sungai Kalimantan Tengah yang ganas. Pun pernah dalam perjalanan ada yang hampir terlempar ke kawasan kebun rotan karena dihempas pusaran air.
Itulah perjuangan mengentas kemiskinan di Kalimantan.
*Damianus Siyok , penulis dan penerbit terutama buku-buku tentang Dayak
Catatan Kusni Sulang: BISA! KITA BISA!
Penyunting: Andriani SJ Kusni
Sebelum ke Kalimantan Tengah (Kalteng), saya banyak berkegiatan bersama teman-teman di Institut Dayakologi (ID) dan Yayasan Pancur Kasih, Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar).
Ketika saya diminta ke Kalteng, kawan-kawan dari Kalimantan Barat, seperti juga kawan-kawan dari Kalimantan Timur (Kaltim) serta Jakarta, pun aktif dan konkret membantu saya bekerja dan sampai sekarang, antara kami terjalin suatu hubungan emosional yang kuat didasarkan pada suatu mimpi bersama: ‘mengangkat batang terendam agar kembali bisa berdaun dan berbuah’, bila menggunakan pepatah Dayak Kanayatn. Dalam bahasa Dayak Ngaju pepatah berhakikat sama dengan “Manggatang Utus”.
Dua ungkapan di atas sama-sama menunjukkan bahwa masyarakat Dayak dalam keadaan termarjinalisasi. Dihadapan keadaan terpuruk demikian, sekelompok kecil anak muda berpandangan bahwa daripada ‘mengutuk malam lebih baik menyalakan lilin’.
Lilin apakah itu yang patut dinyalakan?
Dalam sebuah diskusi pada kelompok kecil yang tak sampai sepuluh orang itu, pertanyaan yang dibahas: ”Mengapa Dayak terbelakang atau termarjinalisasi?” Pertanyaan yang sesungguhnya ada di tengah masyarakat Dayak.
Umum menjawabnya, karena miskin. Mengapa miskin? Karena bodoh. Mengapa bodoh? Karena miskin! Demikian berputar-putar tanpa mampu memberikan jawaban yang memberikan jalan keluar.
Apakah betul Dayak miskin? Lalu pertanyaan berlanjut. Apakah kalian punya rumah? Dijawab: Ada! Apakah kalian punya tanah? Dijawab: Punya! Punya kebun karet? Punya! Kebun rotan? Punya!
Kalau begitu kalian tidak miskin-miskin amat. Kusni lebih miskin dari kalian. Ia tidak punya apa-apa, kecuali kaki, tangan dan kepalanya. Harta benda ia tak punya. Kalau begitu, apakah kalian (warga masyarakat Dayak) bisa menabung Rp 1.000, – (seribu rupiah per bulan) sebagai modal bekerja lebih lanjut? Dijawab pasti bisa, bahkan Rp10.000, – per bulan pun bisa. “Nah, kalau begitu simpan uang Rp 1.000, – atau Rp10.000, – itu di Credit Union (CU).
Dengan latar keadaan demikianlah maka CU Pancur Kasih berdiri dan berkembang di Kalimantan Barat yang kemudian menjalar ke Kalimantan Tengah. CU ini kemudian berhasil mengumpulkan aset dari para anggotanya hingga miliaran rupiah dan terus bertambah. Para anggota atas dasar proposal usaha mendapat pinjaman dari CU dan didampingi agar usaha itu tidak terbengkalai. Berkat adanya CU ini warga Dayak memperoleh jalan keluar dari himpitan keterpurukan ekonomi. “Kita tidak kaya, tapi kalau perlu rumah, bisa beli rumah. Kalau sakit, ada uang untuk berobat. Anak sekolah bisa dibiayai,” demikian Stepanus Djuweng, salah seorang dari sekelompok kecil di atas menggambarkan perkembangan setelah ada CU.
Saya datang ke Kalimantan Tengah membawa ide tentang CU ini. Tapi, untuk mendirikan, sumber daya manusianya tidak ada. Jalan keluarnya? Ya, belajar! Belajar perlu uang. Ya, dicari! Teman-teman Kalimantan Barat mau memberi saya uang untuk mengirim teman-teman Kalimantan Tengah ke Kalimantan Barat atau tempat lain yang ada CU-nya. Saya tidak mau. Karena uang mudah didapat, mudah juga menguapnya karena tidak ada atau rasa tanggung jawabnya kurang.
Teman-teman kemudian saya tanya: Apa di Palangka Raya ada orang Dayak? Dijawab: Ada. Ada seratus? Dijawab: Ada! Kita ambil 25-50 orang saja. Kita datangi mereka dan minta solidaritas pada mereka agar kita bisa mengirimkan teman untuk pergi sekolah atau belajar sambil menjelaskan tujuan dan rencana selanjutnya. Singkatnya, dana pun terkumpul lebih dari yang diperlukan.
CU Bétang Asi berdiri, Koperasi CU Betang Asi pada 26 Maret 2003, ketika oleh satu dan lain sebab saya harus meninggalkan Kalimantan Tengah. Tapi, sumber daya manusianya sudah ada. Embrio CU sudah dibuat. Barangkali cerita awal ini pun dilupakan atau dianggap tidak ada atau dipandang tidak penting. Teman-teman dari Kalimantan Barat intens mendampingi CU di Kalimantan Tengah yang kemudian kian berkembang.
Melihat perkembangan pesat ini, Stepanus Djuweng mengajukan ide agar dibangun toko serba ada, yang sekarang bernama KPD. Tadinya, tidak sedikit yang memandang ide ini seperti tak mungkin terwujud, seperti halnya sebelum teve swasta berkembang di Indonesia, di Institut Dayakologi sudah muncul ide untuk mempunyai stasiun teve sendiri. Sekarang, stasiun teve sendiri itu pun sudah ada di Kalimantan Barat, bahkan lebih dari satu
Apa yang dikatakan oleh hasil-hasil kecil tapi sangat berarti di atas?
Ia tegas dan jelas mengatakan: Bisa! Kita bisa! Dayak bisa! Keterpurukan tidaklah langgeng dan bukan jalan buntu. Credit Union Bétang Asi dan Koperasi Persekutuan Dayak (KPD) dan mungkin juga ada hal positif lain yang akan menyusul, adalah saling berhubungan, saling topang. Dikatakan juga oleh pengalaman di atas, bahwa perubahan maju, tidak bisa mengabaikan tim pemikir berkomitmen manusiawi sebagai kekuatan inti dari upaya menjadi minoritas kreatif. Secara konsepsional, sesungguhnya sudah dirumuskan oleh tetua Dayak dalam apa yang mereka simpulkan ke dalam ide tentang manusia Dayak Ideal yaitu: manusia mamut-ménténg, pintar-harati, maméh-ureh, tiga karakter yang tak boleh dipisah-pisahkan.
Dalam rangka merayakan hari jadinya yang ke-20 pada 14 Mei 2024 mendatang, KPD akan menyelenggarakan Seminar Internasional “PAKAT DAYAK”. Perayaan dan Ucapan Syukur “KPD Night”, “Family Day-Gathering” Bazar dan UMKM Expo, Diskon Belanja dan kegiatan sosial lainnya.
Seyogyanya, Seminar Internasional dengan para narasumber antara lain Dr. Agustin Teras Narang, S. H., Dr. Ir. Willy M. Yoseph, M.M., Dr. Ringah Anak Kanyan, Suroto, Stepanus Djuweng, Rita Sarlawa, S. E., M. Si., dan Ambu Naptamis, S. H., M. H., bisa menyimpulkan pengalaman secara mendasar dan menjelmakan kapakat (persatuan) sebagai kenyataan.
Selamat Ulang Tahun, KPD!***

Halaman Budaya Sahewan Panarung | 14 April 2024 | Andriani SJ Kusni: SANSANA KAYAU
Radar Sampit, Minggu, 14 April 2024

Sansana kayau adalah puisi lisan, diciptakan dan dinyanyikan langsung pada saat pergelaran. Di Daerah Aliran Sungai Katingan, terutama di Katingan Hilir dan Hulu, sansana kayau sampai sekarang masih hidup dan dinyanyikan, biasanya dipertunjukan pada saat pesta, upacara-upacara adat seperti menerima tamu dalam upacara pemotongan pantan, pesta perkawinan, bahkan dalam keseharian.
Puisi yang dinyanyikan tersebut diciptakan oleh penyair individual, kemudian disambut secara beramai-ramai oleh seluruh orang yang hadir. Para pelantun nyanyian puisi (disebut pasansan) bisa melantunkannya secara acapela (tanpa musik) dan bisa juga dengan iringan suling balawung dan kacapi.
Para Pasansana berdialog menggunakan puisi (sansana kayau), paduan antara kolektivitas dan individu. Pada puisi berbentuk sansana kayau ini, hubungan serasi antara individu dan kelompok dalam masyarakat Periode Bétang tergambarkan seperti juga dicerminkan dalam tari pergaulan Manasai–yang pada masa Pemerintahan Soekarno pernah diangkat secara resmi oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai tari pergaulan nasional.
Dikarenakan Sansana Kayau diciptakan dan dilantunkan secara langsung (semacam karya improvivasi) dan tanpa menggunakan teks terlebih dahulu pada saat pementasannya, maka dari para pansansana dituntut penguasaan bahasa yang baik, dalam hal ini Bahasa Katingan, keterampilan, dan pengetahuan filsafat Kaharingan yang padan serta kecekatan membaca keadaan dan kecepatan menganalisanya. Dengan pengetahuan dan penguasaan serta keterampilan demikian, baru bisa diharapkan akan lahir karya sansana kayau yang bermutu tinggi.
Sansana Kayau menggambarkan hubungan Uluh Katingan (Orang Katingan) dengan alam, kekuasaan alam lain, hubungan antarmanusia. Artinya, sansana kayau dilahirkan oleh masyarakat Suku Dayak Katingan, oleh alam dan kehidupan manusia serta digunakan dalam kehidupan sampai hari ini.
Bentuk Sansana Kayau
Secara teknis bentuk (form) Sansana Kayau terdiri dari tiga bagian, yaitu: 1) Prolog; 2) Tubuh Sansana; 3) Epilog.
Prolog dan Epilog dinyanyikan bersama-sama dalam irama tertentu dengan kata-kata: Oi, nanai, nanai, nanai, nanananai, nanai, oiiii nanai.Setelah itu, Pansansana secara tunggal (soloist) menyanyikan puisinya dan pada akhirnya ditutup untuk kemudian dilanjutkan lagi dengan prolog. Pengulangan lirik untuk prolog dan epilog sama.
Subtansi
Subtansi pesan dan isi puisi terdapat pada Tubuh Sansana, puitisitas Tubuh Sansana terdapat pada keseluruhan Tubuh Sansana, baik di awal (aliterasi), di tengah ataupun di akhir (coda).
Sansana Kayau dengan gampang berkembang menjadi sebuah naskah cerita drama, novel atau roman, hal ini terbukti oleh adanya karya epik Sansana Bandar, Sansana Kayau Pulang (warisan para Pansansana terdahulu), dan lain-lain.
Dirangkum dari: https://jurnaltoddoppuli.wordpress.com/2010/04/
REVITALISASI TRADISI LISAN DAYAK NGAJU: SANSANA
Oleh: Basori* | Penyunting: Andriani SJ Kusni
Sansana adalah puisi lisan, diciptakan dan dinyanyikan langsung pada saat pergelaran. Di daerah Aliran Sungai Katingan, terutama di Katingan Hilir dan Hulu, sansana sampai sekarang masih hidup dan dinyanyikan, biasanya di pertunjukan pada saat pesta, pada upacara-upacara adat seperti menerima tamu dalam upacara potong pantan, pesta perkawinan, bahkan dalam keseharian (Kusni, 2010).
Puisi yang dinyanyikan tersebut diciptakan oleh pesansana yang kemudian disambut secara beramai-ramai oleh seluruh orang yang hadir. Pasansana bisa melantunkannya secara acapela (tanpa musik) dan bisa juga dengan iringan suling Balawung dan Kacapi. Paduan antara kolektivitas dan individu dalam seni sansana menggambarkan hubungan serasi antara individu dan kelompok dalam masyarakat periode rumah Betang, hubungan yang juga dicerminkan juga pada tari pergaulan Manasai.
Karena sansana dituturkan secara langsung tanpa menggunakan teks, pada saat pementasannya, maka para Pasansana dituntut menguasai bahasa Dayak Ngaju yang baik, serta keterampilan dan pengetahuan filsafat Kaharingan (agama tua suku Dayak) yang memadai.
Sansana menggambarkan hubungan Uluh Dayak (orang Dayak) dengan alam, kekuasaan alam lain, hubungan antara manusia, artinya sansana dilahirkan oleh masyarakat Dayak Ngaju, oleh alam dan kehidupan manusia (Kusni, 2010).
Sansana biasanya digelar berhubungan dengan adanya suatu hajatan. Biasanya hajatan itu timbul dari janji-janji tertentu atau wujud rasa syukur karena telah tercapainya sesuatu yang diharapkan. Misalnya, seseorang berjanji kepada diri sendiri akan mengundang tukang sansana apabila mempunyai anak laki-laki tampan, tanaman padinya panen dengan memuaskan, perjalanan berhasil dengan selamat dan lancar, dan sebagainya. Sansana juga dapat digelar apabila seseorang atau keluarga menghendaki keluarga yang damai, murah rezeki, atau ingin menyatakan rasa syukur dan gembira atas lahirnya seseorang bayi dengan selamat dan sebagainya.
Cerita yang diangkat dalam sansana adalah cerita legendaris yang berisi kisah seorang tokoh super, yang memiliki banyak pengetahuan, pengalaman, kekuatan lahir batin, kecerdasan, serta budi pekerti yang luhur. Tokoh super ini disebut bandar. Dengan demikian dapat dikatakan, bandar sebenarnya bukan nama tokoh, tetapi gelar tokoh legendaris sehingga muncul sebutan Bandar Tumanggung, Penembahan, Bandar Panjantrahan, Bandar Ratu Anom, Bandar Huntup Batu Api, dan lain-lain.
Sansana dapat digolongkan dalam bentuk prosa liris karena cerita yang disampaikan berirama, meskipun iramanya sangat sederhana dan monoton. Di luar ciri tersebut, pilihan kata dalam sansana dan penyusunannya tampak agak menyimpang dari aturan-aturan bahasa Dayak Ngaju yang dipergunakan sehari-hari oleh masyarakat.
Pemilihan sansana sebagai subjek tulisan disebabkan banyaknya karya sastra masyarakat Kalimantan Tengah, khususnya masyarakat Dayak Ngaju yang belum secara tuntas diteliti. Salah satunya adalah seni sansana. Sampai saat ini, penelitian dan pendokumentasian sastra lisan Dayak Ngaju (dan Dayak pada umumnya) amat sedikit.
Sansana, sebuah proses bernyanyi yang diiringi kecapi sebagai alat musiknya dan ditujukan sebagai penghibur hati setelah seharian bekerja di ladang merupakan media mengomunikasikan misi kebaikan, penceritaan riwayat seseorang yang dianggap sangat terhormat dan sangat berjasa, serta tentang percintaan. Tetapi, belakangan kesenian ini sudah semakin hilang dari kebiasaan masyarakat. Hal itu disebabkan kecanggihan teknologi yang menawarkan lebih dari sekadar sebuah sansana, sedangkan upaya secara sistematis untuk mempertahankan keberadaan sansana sepertinya tidak terlaksana dengan baik. Hal ini terbukti dengan kurang menguasainya kaum muda dalam kesenian ini.
Kenyataan bahwa dalam perkembangan masyarakat dan peradaban yang mengharuskan masyarakat itu mengikuti perubahan yang ada, seolah sudah tidak bisa dihindari. Hal ini membuat masyarakat tersebut secara tidak sadar meninggalkan budaya lama kemudian menggantikannya dengan budaya yang baru. Seiring dengan kemajuan zaman, semakin tertinggal pula kesenian-kesenian daerah dari hati masyarakat. Hal ini pun terjadi pada masyarakat Kalimantan Tengah, khususnya Dayak Ngaju.
Satu hal yang bisa kita lihat adalah tidak adanya regenerasi dalam bidang kesenian, khususnya kesastraan yang benar-benar intens untuk melestarikan budaya tersebut. Untuk itulah kajian ini dilakukan, agar khasanah sastra yang ada dalam suku Dayak Ngaju ini tidak hilang begitu saja. Di samping itu, kajian ini juga dimaksudkan sebagai suatu upaya penulisan karya-karya sastra yang memang tidak ada, karena pada umumnya di Kalimantan Tengah berlaku sastra lisan sehingga jika tidak ada upaya intensif dalam pencatatan dan pembukuannya, akan hilang tanpa meninggalkan bekas ditelan oleh zaman yang bergerak demikian cepat. Di samping itu, nilai-nilai yang tekandung dalam sansana sebagai bahasa hati dan sosial akan hilang begitu saja jika tidak segera menjadi perhatian yang serius. Utamanya bagi kaum intelektual yang bergerak di bidang kebudayaan serta kesenian dan kesastraan.
Tulisan ini diharapkan bermanfaat bagi pemerintah, masyarakat Dayak Ngaju, dan masyarakat umum. Untuk pemerintah, penelitian ini bermanfaat sebagai salah satu sumber dasar informasi dalam pengambilan keputusan daerah dan bahan pertimbangan bagi pelaksana pembangunan di lapangan. Untuk masyarakat Dayak Ngaju, penelitian ini dapat merangsang generasi muda untuk lebih mencintai sastra lisan Dayak Ngaju; menjadi bahan pertimbangan bagi dasar pengembangan diri masyarakat dalam bidang kesenian dan kebudayaan; serta lebih meningkatkan rasa kebanggan diri terutama dalam pembangunan bangsa menuju manusia yang bermartabat. Untuk masyarakat umum, penelitian ini dapat merangsang para sastrawan, ilmuwan, dan seniman untuk menggali lebih dalam sastra lisan Dayak Ngaju dan bisa menjadi dasar penelitian lanjutan, serta membuka pengetahuan masyarakat luas tentang sastra lisan suku Dayak Ngaju.
Landasan Teori
Tentang revitalisasi, peneliti menggunakan teori Pudentia (2008) dan Sibarani (2012). Sibarani (2014: 299) menyatakan bahwa model revitalisasi lisan dan pelestarian tradisi lisan yang ditawarkan meliputi Sumber Daya Manusia (SDM) budaya yang bergerak dalam bidang tradisi lisan, metode revitalisasi dan pelestarian tradisi lisan, dan paradigma revitalisasi dan pelestarian tradisi lisan yang mencakup pelaku, pendukung, akademisi, pemerintah, promotor budaya, dan industriawan budaya. Kemudian, ia menambahkan bahwa komponen revitalisasi mencakup penghidupan/pengaktifan kembali, pengelolaan, dan pewarisan tradisi lisan serta tiga komponen pelestarian, yakni: perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan tradisi lisan.
Sibarani (2012: 307) menyatakan bahwa tipe revitalisasi dan pelestarian tradisi lisan dapat dilakukan secara formal melalui pendidikan formal, secara nonformal melalui sanggar-sanggar atau lembaga-lembaga adat, dan secara informal melalui kesadaran sendiri belajar di masyarakat. Ketiga tipe revitalisasi dan pelestarian tradisi lisan itu sebaiknya dilakukan secara bersama-sama demi pewarisan tradisi lisan di masa mendatang.
Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan langkah-langkah penelitian etnografi. Langkah-langkah etnografi itu dipaparkan dalam bagian berikut:
- Membuat Catatan Etnografis. Membuat catatan etnografi merupakan tindakan sebagai jembatan antara temuan dan deskripsi, yang menghubungkan temuan dan deskripsi menjadi tunggal, proses yang komplit. Temuan-temuan menemukan caranya dalam akhir tulisan etnografi. Membaca catatan ini di lapangan akan menuju kepada temuan-temuan tambahan. Adanya umpan balik ketika menulis etnografi yang mengarah kepada temuan-temuan baru dan tambahan-tambahan untuk catatan etnografi. Bisa disimpulkan bahwa temuan etnografi akan dilanjutkan dengan membuat catatan etnografi dan berakhir pada deskriptif etnografi. Catatan etnografi akan mengumpulkan temuan-temuan dari sudut pandang penutur dan menuliskan etnografi akhir (deskripsi) yang merupakan perolehan yang teliti dari proses terjemahan.
- Menetapkan Situasi. Berdasarkan informasi dari para informan, peneliti menetapkan situasi yang akan diteliti. Spradley (1979: 39) menyatakan bahwa setiap situasi sosial diidentifikasi menjadi tiga bagian mendasar yaitu: tempat, aktor (pelaku), dan aktivitas. Dalam hal ini, lokasi atau tempat penelitian sesuai dengan hasil wawancara dan pengamatan peneliti, maka lokasi penelitian ditentukan di Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya dan Kecamatan Sanaman Mantikei, Kabupaten Katingan. Untuk aktor/pelaku, ditentukan berdasarkan kriteria informan yang baik sesuai dengan pendapat Spradley.
- Melakukan Observasi Partisipasi. Spradley (1979: 54) menyatakan bahwa observasi partisipan melakukan observasi dengan dua tujuan: (1) untuk terlibat dalam aktivitas dan situasi tertentu, (2) untuk mengobservasi aktifitas, pelaku, dan aspek-aspek fisik dari situasi tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan obsevasi partisipasi dengan melakukan hal-hal yang berkaitan dengan pemerolehan informasi mengenai Sansana.
- Membuat Catatan Etnografi. Rekaman dalam penelitian ini mencakup rekaman secara audio-video untuk mendapatkan rekaman sansana dan wawancara sekaligus dapat mengobservasi kegiatan tersebut.
Sansana, Penciptaan, dan Persebarannya
Sebagai puisi lisan tradisional, umumnya penciptaan sansana berlangsung secara spontan atau langsung di depan khalayak pada saat pertunjukan. Setelah itu pesansana akan melantunkan sansananya sesuai dengan suasana yang terjadi saat itu. Sansana biasanya menceritakan tokoh-tokoh yang memiliki banyak pengetahuan, pengalaman, kekuatan lahir batin, kecerdasan, serta budi pekerti yang luhur. Tokoh-tokoh dalam sansana ini merupakan tokoh-tokoh pemimpin dalam masyarakat Dayak.
Pada saat ini, amat sedikit orang yang mampu menciptakan sansana. Masyarakat Dayak Ngaju sendiri sadar bahwa menciptakan sansana ternyata tidak mudah, kesulitan terutama ada pada penciptaan syair. Untuk dapat menciptakan sebuah syair yang indah, seseorang dituntut untuk memiliki pengetahuan yang memadai mengenai bahasa (Dayak Ngaju), wawasan yang cukup tentang kehidupan budaya masyarakat, keterampilan menggali dan mengolah tema, dan memiliki imajinasi yang kuat. Bahasa Dayak Ngaju sendiri saat ini mengalami pergeseran, terutama pada remaja dan anak-anak muda yang mulai menggunakan Bahasa Banjar dalam pergaulan mereka sehari-hari. Hal ini tentu saja memengaruhi keberadaan sansana itu sendiri, meski mungkin masih ada sebab lain yang lebih dominan.
Karena keterbatasan tersebut, umumnya, pencipta sansana dianggap sebagai seorang yang istimewa, meski dalam kehidupan bermasyarakat hal itu tidak memengaruhi sikap masyarakat, dalam arti ia tidak memeroleh perlakuan khusus.
Sejak mulanya, sansana tercipta sebagai media hiburan, pendidikan, dan ekspresi budaya masyarakat Dayak Ngaju. Berdasarkan pada hal tersebut, sansana tersebar luas di kalangan masyarakat di Kalimantan Tengah, dengan berbagai istilah yang melabelinya. Sansana, pada akhirnya menjadi lambang identitas masyarakat Dayak Ngaju. Sesuai dengan keberadaan etnik Dayak Ngaju sebagai kelompok etnik terbesar (dalam jumlah dan luas wilayah sebaran) di Kalimantan Tengah, seluas itu pula wilayah sebaran sansana. Tradisi migrasi etnik juga ikut memengaruhi proses persebaran sansana ke wilayah yang lebih luas.
Penyair sansana tidak lahir dari pendidikan formal. Juga tidak dari pewarisan yang turun-temurun dari generasi tua ke generasi di bawahnya secara sengaja. Penyair sansana lahir dari proses alamiah dengan adanya beberapa pemuda yang suka kemudian meniru dan belajar bagaimana bersansana. Mereka belajar dengan memerhatikan bagaimana seorang pasansana itu melantunkan nyanyian-nyanyian yang disesuaikan iramanya. Ada pula pewarisan model keturunan, seorang damang atau balian akan mewariskan kemampuannya dalam bersansana pada anaknya.
Dalam proses peniruan ini, tidak mustahil memunculkan perubahan bentuk dan pengembangan, termasuk di dalamnya adalah perubahan nada pada posisi tertentu. Dari sini terjadi proses resepsi produktif. Pilihan-pilihan kata yang digunakan amat tergantung pada pelantun dan suasana yang terjadi pada saat pelantunan. Sebagaimana umumnya sastra lisan, para penyair sansana juga tidak mencantumkan nama atau identitas penciptanya. Setiap sansana yang tercipta merupakan milik kolektif masyarakat. Hal ini terjadi sepanjang pewarisan sansana secara lisan.
Revitalisasi Sansana, Kekayaan Budaya Dayak Ngaju
Tradisi lisan, apa pun bentuknya kian memudar dan terancam seiring perubahan orientasi hidup dan kebudayaan masyarakatnya. Hal itu tidak bisa dimungkiri. Begitu juga dengan sansana, meskipun di daerah-daerah tertentu kita masih menemukan keberlangsungannya. Misalnya, di wilayah hulu Sungai Kahayan, Katingan, dan Kapuas, tradisi bersansana, karungut, deder, dan upacara-upacara tradisional yang tentunya dilengkapi dengan tradisi-tradisi lisan masih bisa kita dapati.
Berikut ini beberapa hal yang ditengarai menjadi sebab makin hilangnya sansana di kalangan masyarakat Dayak Ngaju:
Pertama, faktor intern masyarakat Dayak sendiri. Masyarakat tidak atau kurang bisa lagi menghargai diri dan budaya sendiri. Menjadi Dayak dan berbudaya Dayak dianggap sebagai “primitif” dan tidak modern. Menjadi tidak ”keren” kalau berdialog dengan siapa pun menggunakan bahasa Dayak (dengan lingkungan sesama Dayak sendiri bahkan). Keadaan ini membuat masyarakat diam-diam melakukan bunuh diri budaya, mengasingkan diri dari komunitas, dan kehilangan ketahanan budaya. Perubahan pola hidup menuju kemodernan telah memosisikan generasi muda semakin jauh berada di luar sansana. Mereka semakin menjauhi sansana karena kurang mampu berbahasa Dayak Ngaju, di samping irama sansana yang cenderung monoton dan membosankan jika dibandingkan dengan hingar-bingar musik luar.
Kedua, pergeseran pemakaian bahasa. Generasi muda masa ini lebih mahir berbahasa Banjar daripada berbahasa Dayak Ngaju. Hal ini dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniati (2008) terhadap seratus responden mahasiswa etnik Dayak di Palangka Raya. Hasil penelitian itu menunjukkan bahwa banyak mahasiswa etnik Dayak sudah tidak mahir lagi dalam berbahasa Dayak Ngaju.
Ketiga, pola persebaran dan pewarisan yang bersifat individual dan tidak terorganisasi dengan baik. Pewarisan dalam bentuk demikian nyata-nyata tidak efektif membentuk generasi penerus. Generasi muda masa ini sudah gagap budaya sendiri. Mereka lebih suka dengan permainan yang lebih “modern” dengan gitar, piano, drum, dan sebagainya.
Keempat, pendokumentasian yang tidak terbarukan lagi. Pendokumentasian sansana dengan kaset yang hanya bisa didengar melalui tape recorder terasa tidak ada artinya pada saat dunia sudah sangat akrab dengan media video youtube.
Kelima, peran media massa, RRI, yang makin mengurangi jumlah jam siar sansana. Media massa cetak pun sudah tidak ada lagi yang memuat syair-syair sansana. Penerbitan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sangat terbatas dalam hal jumlah cetakan dan sebarannya.
Keenam, peran pemerintah yang diharapkan bisa menjadi benteng terakhir keberadaan sansana juga semakin berkurang. Media festival hanya menjadi semacam rutinitas tahunan yang bahkan tidak bergerak. Dari tahun ke tahun yang menghadiri dan mengikuti lomba adalah peserta yang itu-itu juga.
Festival yang diharapkan mampu menjadi jaring regenerasi nyata telah kehilangan fungsi dengan makin kuatnya keinginan untuk menjadi pemenang tanpa memerhatikan keberlangsungan regenerasi. Yang paling mendasar sebenarnya adalah masuknya tradisi lokal ini dalam kurikulum sekolah dalam materi muatan lokal atau ekstrakurikuler. Faktor ini tampaknya tidak digarap dengan sungguh-sungguh bahkan beberapa sekolah di Palangka Raya justru memasukkan bahasa Inggris sebagai muatan lokal (hal yang aneh). Pewarisan dan penyebaran lewat sanggar-sanggar seni juga belum kelihatan hasilnya.
Berkaitan dengan masalah-masalah tersebut, revitalisasi sansana menjadi penting untuk mulai dipikirkan dan menjadi program mendesak dalam upaya untuk melestarikan kebudayaan ini. Revitalisasi ini juga mesti mempertimbangkan bahwa sansana merupakan puncak kebudayaan Dayak. Segala sesuatu yang sudah mencapai puncak tentu tidak akan bisa berkembang lebih baik lagi. Langkah yang bisa diambil adalah menciptakan sesuatu yang baru atas dasar unsur-unsur yang sudah mencapai puncak itu. Tentu saja ini tidak bermaksud untuk menggugat atau bahkan mengganti sesuatu yang berada di puncak itu. Ini merupakan salah satu cara untuk mengembangkan dan sekaligus melestarikan kebudayaan dalam fungsinya. Sebagaimana seni campur sari dalam kebudayaan Jawa.
Beberapa langkah yang sangat mungkin untuk bisa dilakukan terkait dengan masalah tersebut antara lain: pertama, mengembalikan fungsi dan peran bahasa Dayak Ngaju sebagai bahasa pergaulan sehari-hari. Lingkungan keluarga menjadi garda depan untuk membiasakan diri menggunakan bahasa Dayak Ngaju; kedua, bahan ajar muatan lokal bahasa dan budaya Dayak Ngaju juga mesti disiapkan dengan baik. Hal ini tentu saja menuntut peran yang lebih banyak dari pemerintah daerah. Balai Bahasa Kalimantan Tengah sudah menyusun Tata Bahasa Dayak Ngaju, Kamus Dayak Ngaju. Hal ini perlu dilanjutkan dengan penyusunan bahan ajar muatan lokal; ketiga, pendokumentasian dengan media terbarukan. Sansana bisa dibuat dalam bentuk film animasi yang diharapkan akan menarik minat para pelajar untuk mengetahui dan belajar bersansana; keempat, pasansana harus lebih kreatif dalam bersansana, menciptakan pola baru dari pola-pola yang sudah ada. Kreatif memilih tema dan menggunakan kata.
Simpulan
Sansana sudah semakin kehilangan peminat seiring perkembangan teknologi. Apabila sansana tidak bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi ini, sansana akan semakin hilang. Apabila hal ini tidak diperhatikan secara sungguh-sungguh, dikhawatirkan kehidupan sansana akan surut dan hilang dalam satu generasi ke depan. Kusni, penyair Dayak yang tinggal di Paris, pernah mengungkapkan gagasan revitalisasi terhadap sansana dalam pertemuan Sastrawan Borneo, 2005. Tampaknya, hal itu perlu segera kita sambut sebagai bagian dari pemertahanan dan pengembangan sansana di masa mendatang. (Sumber: Jurnal Sastra Lisan, Volume 1, Nomor 1, 2021).
*Basori, Peneliti pada Pusat Riset Manuskrip, Literatur, dan Tradisi Lisan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Disunting berdasarkan keperluan penyiaran ini.

Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 H
Halaman Masyarakat Adat | 7 April 2024 | Catatan Kusni Sulang: SEJARAH, RUANG TERBUKA HIJAU, TEMPAT PARKIR DAN PEMAJUAN ZAMANI
Radar Sampit, Minggu, 7 April 2024 | Penyunting: Andriani SJ Kusni


Gedung KONI yang dibangun pada tahun 1974, 17 tahun setelah Kalimantan Tengah (Kalteng) berdiri sebagai provinsi otonom seusai pemberontakan bersenjata rakyat—terutama masyarakat Dayak—setelah Lebaran ini akan dibongkar dan dijadikan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH).
Gedung ini diresmikan oleh Wakil Presiden Sultan Hamengku Buwono IX pada 1 Agustus 1975. Awalnya digunakan sebagai Gedung DPRD Kalteng di mana banyak keputusan-keputusan yang berperan dalam perkembangan Katleng telah diambil sedangkan Gedung DPRD Kalteng yang sekarang (terletak di depan Tugu Soekarno), tadinya digunakan sebagai Kantor Gubernur. Karena itu, Gedung KONI dipandang sebagai salah satu gedung bersejarah dan pada tempatnya dijadikan sebagai cagar budaya.
Permintaan untuk menjadikan Gedung KONI diberikan status cagar budaya sudah pula diajukan dan didaftarkan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebagaimana diperlihatkan oleh dokumen-dokumen seperti Surat Edaran Pelindungan Cagar Budaya Gedung KONI Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2288/F.F4/KB.09.02/2024 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Surat Permohonan Peninjauan Kembali Pendaftaran Gedung KONI/Eks DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 800/1054/DPKKO-Umpeg/IV/2024 Pemerintah Kota Palangka Raya Sekretariat Daerah.
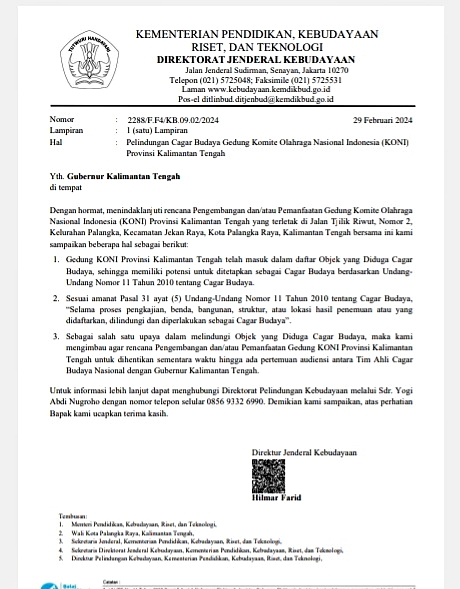
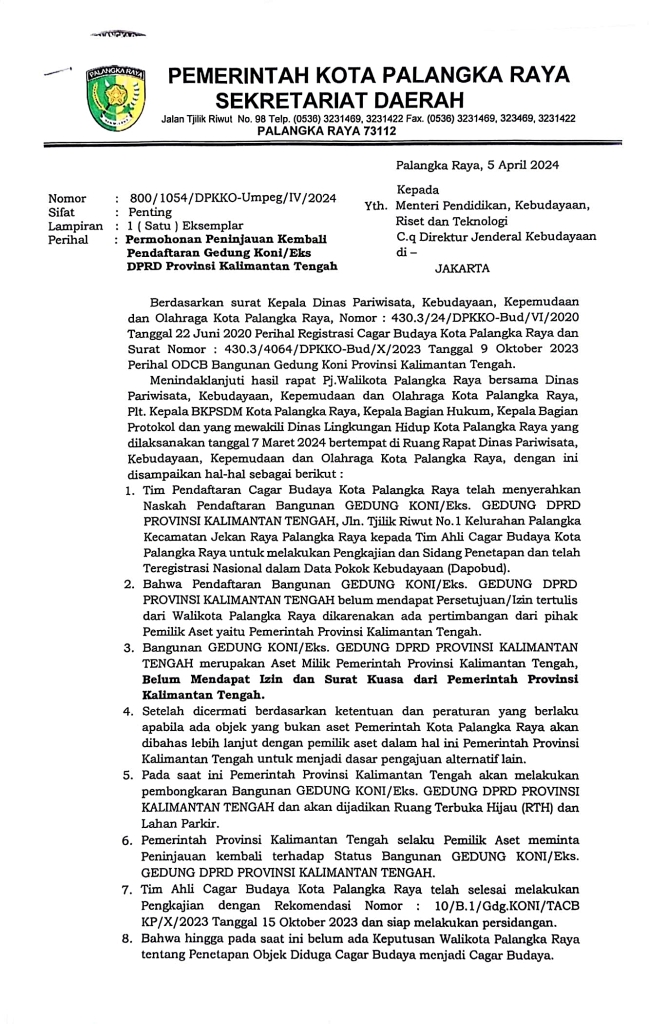
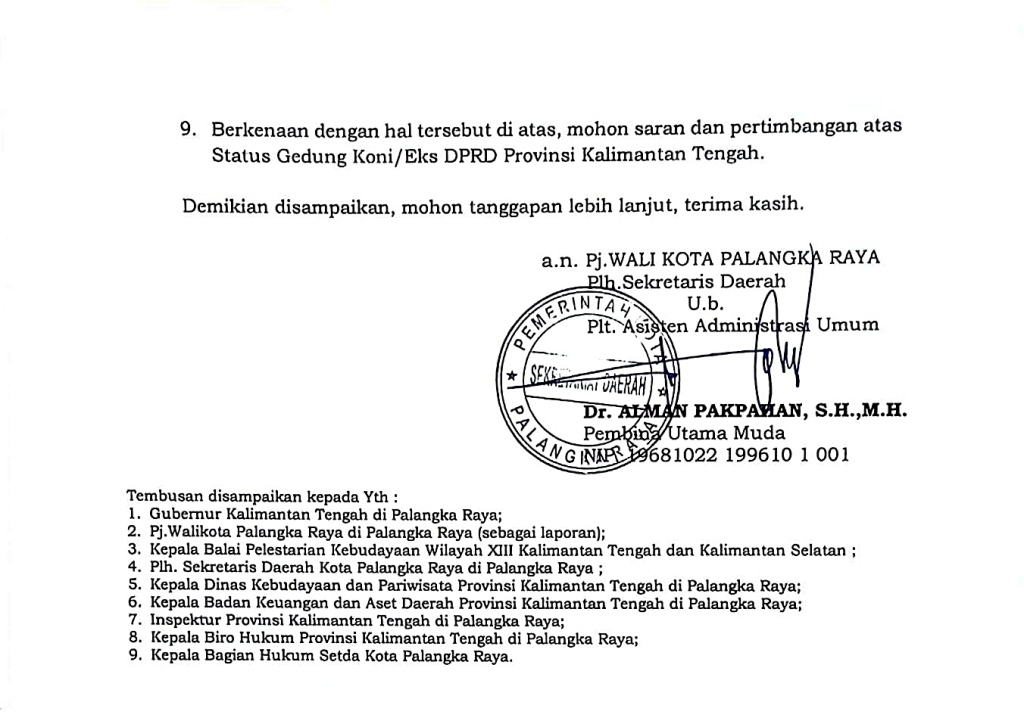
Sekalipun Gedung KONI itu “telah masuk ke dalam daftar Objek yang Diduga Cagar Budaya, Pemerintah Provinsi Kalteng tetap berencana membongkar Gedung KONI Palangka Raya dengan alasan, menurut Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo “menata kawasan sekitarnya secara komprehensif, termasuk membangun Ruang Terbuka Hijau (RTH). Dengan demikian, Bundaran Besar benar-benar menjadi sebuah tempat yang menciptakan multiplier effect (dampak ganda), di antaranya pertumbuhan ekonomi pariwisata hingga sarana edukasi dan rekreasi yang memadai.”
Gubernur Sugianto Sabran (mengutip Wakil Gubernur Edy Pratowo) menjelaskan, pembangunan RTH tersebut direncanakan dengan memugar atau membongkar bangunan eks Gedung KONI atau gedung DPRD lama yang ada saat ini.
Apabila diperlukan, juga termasuk kantor Dispora dan kantor Disnakertrans saat ini sebab kantor atau gedung pemerintahan itu sudah tidak layak dari sisi estetika jika berada di kawasan bundaran.
“Akan lebih tepat jika Bundaran Besar saat ini menyatu dengan kawasan Ruang Terbuka Hijau, dilengkapi playground taman bermain edukatif bagi anak-anak, serta bangunan satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak,” kata Sugianto Sabran (https://kalteng.antaranews.com/berita/683181/wagub-kalteng-ada-keinginan-rth-dan-tempat-bermain-di-bundaran-besar).
Sementara Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalteng Salahuddin mengetengahkan alasan-alasan pembongkaran sbb:
- Karena gedung Koni telah berusia kurang lebih 40 tahun, dari aturan bangunan gedung sendiri usia bangunan gedung dengan K300, K125 dan K150 mendekati usia bangunan 50 tahun mesti dilakukan pembongkaran karena tidak menjamin keamanannya (https://palangkaekspres.co/pemprov-pastikan-tetap-bongkar-gedung-koni/utama/55099/2024/03/27/).
- Gedung KONI dinilai merupakan bangunan yang telah terintegrasi dengan Bundaran Besar Palangka Raya (https://www.borneonews.co.id/berita/335545-setelah-lebaran-gedung-koni-kalteng-dibongkar).
- “Apakah itu diduga cagar budaya, menurut saya itu merupakan kewenangan yang memiliki aset dan secara sah aset tersebut kepunyaan pemprov. Jadi sudah semestinya pihak pemprov yang lebih berhak menentukan, apakah gedung KONI tersebut dijadikan cagar budaya atau tidaknya,” (https://palangkaekspres.co/pemprov-pastikan-tetap-bongkar-gedung-koni/utama/55099/2024/03/27/).
- Salahuddin menyampaikan kewenangan terkait cagar budaya merupakan kewenangan yang memiliki aset (https://kalteng.tribunnews.com/2024/03/27/gedung-koni-kalteng-di-bundaran-besar-palangkaraya-segera-dibongkar-perencanaan-sejak-6-tahun-lalu).
Maka dari itu, pihaknya (Salahuddin –KS) mengaku terkejut saat mengetahui Gedung KONI diduga sebagai cagar budaya. “Jadi jika dibilang saat ini muncul diduga cagar budaya, kenapa baru sekarang, tidak dari enam tahun lalu, mengingat enam tahun yang lalu membuat bangunan terintegrasi dengan bangunan sekitarnya tersebut, kita mengundang semua tokoh masyarakat termasuk budayawan yang ahli tentang cagar budaya, arsitek. Jadi kami saat ini hanya melanjutkan saja,” imbuhnya.
Salahuddin menyampaikan, kewenangan terkait cagar budaya merupakan kewenangan yang memiliki aset (https://kalteng.tribunnews.com/2024/03/27/gedung-koni-kalteng-di-bundaran-besar-palangkaraya-segera-dibongkar-perencanaan-sejak-6-tahun-lalu).
Setelah mengetahui rencana ini, gelombang penolakan pun datang dari berbagai pihak: dari para ahli, anggota-anggota DPRD Kota dan Provinsi, anggota DPD-RI, kalangan mahasiswa, gereja, dan lapisan masyarakat lainnya.
Argumen penolakan umumnya berangkat dari makna sejarah dan pendidikan dari gedung-gedung tua seperti Gedung KONI, yang sesungguhnya bukan tanpa preseden di provinsi ini.
Bahkan pihak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui Dirjen Kebudayaan pun telah bersurat kepada Gubernur Kalteng, H. Sugianto Sabran, menyampaikan tiga hal:
- Pertama, Gedung KONI di Bundaran Besar Kota Palangka Raya telah masuk daftar objek diduga cagar budaya (ODCB) dengan potensi ditetapkan menjadi cagar budaya.
- Kedua, sesuai Undang-undang No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, maka selama dalam proses pengkajian, setiap objek diduga cagar budaya yang didaftarkan, akan dilindungi dan diperlakukan sebagai cagar budaya.
- Ketiga, agar rencana terkait gedung KONI tersebut ditunda hingga ada pertemuan dengan Tim Ahli Cagar Budaya Nasional (https://kaltengdaily.com/kabar-terkini/kemendikbudristek-ri-minta-pembongkaran-gedung-koni-kalteng-ditunda/).
Dalam penolakan terhadap rencana pembongkaran Gedung KONI Palangka Raya ini, yang disampaikan bukan hanya protes, tetapi saran-saran jalan keluar atau alternatif pun dikemukakan.
Terhadap pendapat-pendapat ini, Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo hanya mengatakan, “Ya, kita termasuk mendengarkan semuanya,” (https://prokalteng.jawapos.com/pemerintahan/pemprov-kalteng/28/02/2024/respon-surat-teras-narang-soal-rencana-pembongkaran-gedung-.koni-ini-penjelasan-wagub-kalteng/).
Tapi yang sering saya alami bahwa yang didengar itu biasanya dibiarkan masuk dari telinga kiri, segera keluar dari telinga kanan. Apalagi kalau menyimak argumen Salahuddin bahwa “Apakah itu diduga cagar budaya, menurut saya, itu merupakan kewenangan yang memiliki aset dan secara sah aset tersebut kepunyaan pemprov. Jadi sudah semestinya pihak pemprov yang lebih berhak menentukan, apakah Gedung KONI tersebut dijadikan cagar budaya atau tidaknya.” Pandangan yang memperlihatkan pendekatan kekuasaannya begitu kuat: “Boleh mengatakan apa saja, yang menentukan adalah saya karena saya yang berkuasa”.
Pandangan begini sama sekali tidak memedulikan apakah yang disampaikan dan ‘pura-pura’ didengar itu, benar atau salah secara hakekat. Suatu sikap yang disebut oleh Merton sebagai ‘kepribadian birokratik’ (bureaucratic personality), walaupun dalam praktek, pemahaman terhadap peraturan-peraturan oleh para birokrat itu patut dipertanyakan.
Alasan-alasan yang dikemukakan oleh Salahuddin sebenarnya sangat lemah. Ketiadaan tempat parkir, keamanan gedung sudah tak terjamin, sudah mengajak diskusi para pihak enam tahun silam. Mantan Plt Ketua KONI Kalteng, Christian Sancho mengatakan bahwa gedung KONI masih layak dipakai tidak seperti yang disebut oleh Salahuddin sedangkan mengenai diskusi dengan para pihak yang disebut oleh Salahuddin, menurut Sancho, “Rapat terkait pembongkaran tersebut yang diundang sangat terbatas, orang-orang yang diundang, merupakan orang-orang yang tidak bisa berbicara seperti saya,” tambah Sancho (https://kalteng.tribunnews.com/2024/03/01/gedung-koni-kalteng-masih-layak-pakai-bangunan-bersejarah-saat-pembentukan-provinsi?page=2).
Terbatasnya ruangan ini membuat saya tidak bisa membahas seluruh argumen dari Wakil Gubernur dan Salahuddin poin per poin. Yang mau saya garis bawahi bahwa penghancuran benda sejarah seperti yang mungkin dijadikan cagar budaya, sama dengan melenyapkan bukti sejarah tentang suatu peristiwa atau hal-ikhwal. Yang dihancurkan tidak bisa kembali lagi. Hilang. Bukti-bukti pun hilang oleh penghancuran itu. Jika langkah begini diteruskan, akan beralasan orang mengatakan bahwa Dayak, Kalteng adalah manusia dan daerah primitif walaupun ada mobil,internet, dan lain-lain.
Jika ini terjadi maka apa yang bisa dibanggakan Dayak dan Kalteng, orang dan daerah yang tak punya sejarah. Secara psikologis akan berkembang pengingkaran diri, mentalitas rendah diri, dasar pembenaran Dayak tidak layak memegang penyelenggaraan Negara dan daerahnya. Bunuh diri budaya akan berkembang. Bukti bunuh diri budaya yang saya sinyalir ini memiliki banyak bukti.
Singkatnya: Penghancuran cagar budaya, yang mungkin dijadikan cagar budaya dan bukti-bukti sejarah adalah suatu kesalahan besar, tindak anti-kebudayaan dan berdampak generatif apalagi atas nama tempat parkir. Sejarah akan mencatatnya memang, tapi tidak dengan penghormatan.
Pemajuan zamani tidak akan terwujud dengan menjadikan diri primitif.***

Halaman Budaya Sahewan Panarung | 31 Maret 2024 | Catatan Kebudayaan Andriani SJ Kusni: SAKULA BUDAYA DAN KONSOLIDASI HASIL
Radar Sampit, Minggu, 31 Maret 2024



Sakula Budaya Desa Sumur Mas Kecamatan Téwah, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah (Kalteng) pada 2 Maret 2024 sudah selesai. Kepada para pelatih dan para peserta diberikan sertifikat yang telah dibingkai rapi, sedangkan untuk pemerintah desa dan kepala sekolah SD dan SMP diberikan sertifikat penghargaan atas partisipasi aktif mereka dalam menyelenggarakan Sakula Budaya.
Sakula Budaya memang dinyatakan selesai tapi kegiatan kebudayaan desa tidak berakhir dan terus berlanjut. Mengapa berlanjut dan bagaimana melanjutkannya?
Para pihak seperti pemerintah desa, pihak sekolah, kepolisian Kecamatan Téwah dan para orang tua peserta Sakula serta para peserta Sakula itu sendiri sangat mengharapkan kegiatan berlanjut. Mereka sangat merasakan kegunaaan adanya Sakula Budaya ini dan juga melihat sedang ditunggu oleh perspektif yang cerah.
Ketika masa Sakula berakhir dan acara tamat Sakula diselenggarakan meriah dengan sambutan dari Dirjen Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalteng dan Kabupaten, para orang tua para peserta Sakula dan guru-guru SD dan SMP bernafas lega, berkata, “Akhirnya kita berhasil.”
Kelegaaan ini gampang dipahami karena Sakula Budaya ini sesungguhnya dimulai terutama bermodalkan semangat dan niat memberikan sesuatu untuk tujuan “Manggatang Utus”.
Penyelenggara yang terdiri dari Yayasan Borneo Institut, Fairventure World Wide (yang kemudian berubah menjadi Good Forest Indonesia), Pemdes, SD dan SMP Desa, awalnya tidak memiliki kelengkapan apa pun. Gendang. gong, kecapi, rebab, kangkanong, pengeras suara, dan lain-lain tidak ada.
Melihat keadaan itu, warga desa mencari pinjaman gong dan gendang. Pemangku adat desa, Mantir Herlison menebang sebatang pohon umtuk dijadikan dua buah kecapi yang digunakan untuk mengiringi pelajar mempraktekkan Karungut. Kusni Sulang, seorang pencinta budaya yang turut membantu penyelenggaraan Sakula, tanpa keengganan “mengemis” bantuan ke berbagai pihak dan mendapatkan bantuan gendang baru dari Kardinal Tarung (Damang Jekan Raya, Palangka Raya), sebuah kecapi dari Hansli Gonak (Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas), teman-teman Jerman yang sempat berkunjung secara spontan menyumbangkan dana untuk membelikan peralatan-peralatan mendesak seperti pengeras suara berukuran kecil yang diperlukan untuk latihan menari. Bahkan empati nyata juga datang dari Andrew, teman Kusni Sulang di Universitas Pittsburgh, Amerika Serikat.
Nampak bahwa kebersamaan merupakan kekuatan yang bisa memberikan hasil di luar bayangan. Kebersamaan bisa digerakkan oleh niat dan tujuan baik dan ketulusan—sesuatu yang langka dalam masyarakat kita hari ini, tapi masih tersisa. Masih ada.
Teringat keadaan demikian, pada acara tamat Sakula, para pelatih, para peserta, orang tua-orang tua anak-anak dan pihak Pemdes bernafas lega bahkan ada yang meneteskan air mata. Menanggapi reaksi demikian, Kusni Sulang mengatakan kepada mereka, “Kita sudah memulai sesuatu dan kita akan jalan terus ke depan. Bukan ke belakang. Dayak itu artinya sama dengan pejuang, bukan pengemis!”
Ide, sikap dan semangat demikianlah yang dituangkan dalam slogan Sakula:”Dayak Hingkat, Dayak Batarung, Dayak Manang. Sakula Budaya: Manggatang Utus” (Dayak Bangkit, Dayak Berjuang, Dayak Menang. Sakula Budaya (untuk) Manggatang Utus”.
Adakah dampak dari slogan ini pada masyarakat desa?
Nampaknya ada. Terdapat beberapa petunjuk. Waktu penyelenggaraan Sakula Budaya di Desa Linau, Kecamatan Rungan, warga desa mengira Sakula Budaya itu hanya belajar main, karungut dan seni lainnya. Ketika mendengar adanya lahap (pekikan tarung diteriakkan) disusun oleh slogan di atas, nampak jelas air muka warga desa yang selalu hadir menonton anak-anak mereka latihan, berubah. Seperti orang tersentak. Baru tahu pesan inti penyelenggaraan Sakula.
Di Desa Sumur Mas, setelah sadar akan pesan slogan, setiap melatih, Ugak Sang Pelatih selalu mengenakan ikat kepala (lawung) Merah-Putih. Di desa ini juga, seorang peserta anak SD bercerita penuh antusiasme tentang keindahan alam air terjun 12 lapis yang menurutnya pasti tak ada di bagian dunia lainnya. Ia juga berkisah kepada Kusni Sulang tentang jahatnya penjajahan Jepang. Kemudian, Kusni Sulang ditanyai oleh warga desa.
“Apakah Bué (Bhs Dayak Ngaju: kakek) seorang veteran?”
“Saya veteran?”
“Ya, betul kan, Bué seorang veteran?”
“Bué terlalu kecil pada masa perang gerilya menghalau Belanda dulu, tapi semua anggota keluarga Bué terlibat dalam perang itu,” jawab Kusni.
Cerita-cerita di atas memperlihatkan bahwa pesan slogan Sakula menjalar sampai ke pikiran dan perasaan warga desa. Slogan yang masih diingat oleh peserta didik dan selalu dipekikkan dengan penuh semangat. Serukan saja kata Dayak dengan mengangkat tangan ke atas, maka akan langung terdengar jawaban penuh semangat, “Hingkat, Batarung, Manang dan Manggatang Utus”.
Pasti sikap begini bukanlah kebetulan. Artinya, semangat dan pemahaman yang disebarkan oleh Sakula Budaya di desa, bisa dijadikan bekal spiritual untuk perubahan maju. Dayak itu mau berubah maju.
Untuk melangkah jauh dalam melakukan perubahan maju, yang pertama-tama diperlukan adalah pemajuan pola pikir dan mentalitas bagaimana membuat seluruh warga—terutama yang terpuruk—Hingkat, Batarung untuk Manang dan Manggatang Utus yang seniscayanya.
Lebih lanjut dijelaskan dan ditunjukkan secara konkret, bagaimana hingkat dan batarung, bagaimana manang dan manggatang utus. Penjelasan akan lebih efektif ketika sejarah, filosofi dan nilai-nilai budaya lokal digunakan sehingga etnisitas dan kearifan lokal adalah metode pendekatan yang tak ada kaitannya dengan etnosentrisme. Etnosentris bukan etnosentrisme.
Untuk mengkonsolidasi hasil-hasil yang dicapai melalui Sakula Budaya dan agar kegiatan kebudayaan di desa berlanjut, pada 23 Maret 2024 di Gereja Kalimantan Evangelis desa yang biasa digunakan sebagai tempat latihan, seusai pembagian sertifikat Sakula kepada para peserta, pihak pemerintah desa, pemangku adat dan penyelenggara Sakula Budaya mengadakan rapat bersama untuk menetapkan langkah-langkah tindak lanjut. Rapat memutuskan mendirikan organisasi kebudayaan berakta notaris, dinamai Sanggar Budaya Handep-Hapakat Desa Linau dengan Yater Sahabu sebagai ketua sanggar dan Mantir Herlison sebagai wakil ketua. Selain itu, rapat konsolidasi menetapkan jadwal kerja yang mesti diselesaikan.
Rapat konsolidasi itu memaknai sanggar sebagai wadah melakukan kegiatan kebudayaan dan kebudayaan tidak terbatas pada kesenian. Kesenian sebagaimana dikemukakan oleh Koentjaraningrat, hanyalah salah satu dari tujuh unsur kebudayaan yaitu: sistem peralatan hidup, mata pencaharian, sistem kemasyarakatan, bahasa, kesenian, sistem pengetahuan dan religi. Kebudayaan adalah hal-hal yang bersangkutan dengan budi atau akal (Koentjaraningrat,(1974:19).
Sanggar Budaya inilah selanjutnya yang akan meneruskan pekerjaan Sakula Budaya yang dalam waktu dekat akan diselenggarakan di desa lain, masih di Kabupaten Gunung Mas. Terbayangkan oleh pembaca jika pada suatu hari, desa-desa Kalteng mempunyai Sakula Budaya dan selanjutnya memiliki organisasi kebudayaan masing-masing?
Pelestarian, revitalisasi, transformasi dan pemajuan kemajuan lokal pada saat itu tidak lagi sebatas pernyataan-pernyataan formal standar karena tujuan tersebut mendapatkan cara pelaksanaannya secara terorganisasi dan terencana.***
Sajak Magusig O Bungai
Aku Gaér (Aku Khawatir)
Amas Bukit Naga
Amas Batu Apui
Amas pètak-danum
Mampabèlum lèwu
Bara nyélu ka nyélu
(Emas Bukit Naga
Emas Bukit Apui
Emas kampung-halaman
Menghidupkan lèwu)
Amas panénga
Kataun-kajénta Hattala Ranying
Panguasa karé langit
Bulan matanandau
Akan Utus Dayak-Panarung itah
(Emas anugerah
Tanda kasih sayang Hatatala Ranying
Penguasa seluruh langit
Bulan matahari
Ke Utus Dayak Paanarung kita)
Panjang késah-sarita akangkuh je nakan harian
Huran yuh huran auh ah, amas inggaú
Baranjung-ranjung amas indinu
Baya mbuhen o tambi-bué
Panjang-haї aku
Léwu tatap tapilihi
Huma-séruk tatap baya-baya kia
Nahuang sakula masih bahali?
(Panjang kisah-cerita kepadaku yang lahir belakangan
Dahulu ya dahulu dituturkan, emas dicari
Berkeranjang-keranjang emas diperoleh
Tapi mengapa o kakek-nenekku
Besar dewasaku
Kampung-halaman masih saja tertinggal
Rumah tinggal tetap saja bagai sedia kala
Mau sekolah pun tak ada biaya)
Tahining kuh hung silan léwu
Tégé suara paham nyaring
Diá eh suara riwut-barat, oi aring
Suara té suara buldozer uluh luar
Manggaú amas pétak-danum itah imbongkar
(Di sebelah kampung kudengar
Ada suara nyaring benar
Pasti bukan suara angin ribut, adikku
Suara itu gemuruh bulldozer orang luar
Memburu emas kampung-halaman kita dibongkar)
Aku gaer tambi-bué
Aku gugup mina-mana
Umai-Aba
Je tatisa akangku
Baya rutik jatun am baguna
(Aku khawatir kakek-nenek
Aku gugup paman-tante
Ayah-ibu
Yang tersisa untukku
Hanyalah sampah tanpa guna)
Februari 2024

Halaman Masyarakat Adat | 24 Maret 2024 | Jurnal Perdesaan Kusni Sulang: MEMERIKSA CARA BERPIKIR KITA
Radar Sampit, Minggu, 10 Maret 2024 | Penyunting: Andriani SJ Kusni

Tragedi Sampit 2000-2001, di mana Dayak serta etnik-etnik lain di Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Madura terlibat dalam konflik yang sangat berdarah itu sudah berlalu 24 tahun lalu.
Senyatanya, tidak siapa pun yang diuntungkan dari konflik tersebut. Semua mengalami kerugian, termasuk kehilangan nyawa. Pantar Perdamaian yang didirikan di Sampit setelah tragedi tersebut, seyogyanya bisa selalu mengingatkan kita bahwa keragaman itu sesungguhnya suatu kekayaan dan rahmat yang patut disyukuri, sedangkan keseragaman menyimpan benih petaka, bertentangan dengan kenyataan.
Belajar dari tragedi itu, jadinya merupakan suatu keniscayaan agar kualitas kemanusiaan kita tidak merosot ke taraf kualitas keledai. Kita berhak berbuat salah, asal kita mau dan dengan berani mengoreksi kesalahan itu. Dengan demikian, kita bisa berkembang dengan kualitas baru.
Setelah dua puluh empat tahun berlalu, apakah sikap dan perasaan terhadap etnik lain dalam konflik tersebut di atas sudah pupus? Saya pastikan jawabannya: Belum! Banyak sekali contoh yang saya temukan dalam kehidupan sehari-hari pada kedua belah pihak yang oleh keterbatasan ruangan di sini tidak bisa saya tuturkan dengan rinci.
Dendam dan curiga masih saja ibarat virus menjalar di hati dan kepala–barangkali di kedua belah pihak, tapi yang jelas di kalangan Orang Dayak. Contoh paling baru adalah apa yang saya dapatkan di berbagai Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kalteng, termasuk di Desa Sumur Mas, Kecamatan Téwah, Kabupaten Gunung Mas, pada saat Pilpres Februari 2024 lalu.
Dalam percakapan dengan berbagai pihak, saya ketahui kemudian bahwa warga Dayak tidak mau memilih Paslon Nomor 03, Ganjar-Mahfud karena adanya “faktor Mahfud”. “Mahfud kan Orang Madura? Mengapa memilih Orang Madura?!”
Pernyataan singkat mengandung banyak informasi ini membuat saya tercenung, diam sejenak. Dua puluh empat tahun berlalu, sikap dan perasaan antipati pada Orang Madura masih saja belum pupus. Hampir satu generasi sikap dan perasaan demikian masih merasuk. Sementara, bagaimana Dayak menyelamatkan Madura, Madura menyelamatkan Dayak, dalam konflik berdarah itu sangat-sangat jarang saya dengar diungkap–untuk tidak mengatakan ‘tidak pernah’.
Orang-orang pun tidak pernah menelisik makna perkawinan Tamanggung Panduran dengan seorang puteri Raja Madura yang tercatat pada nama sebuah Desa Panduran di tepi Sungai Kahayan yang masih ada hingga hari ini. Sejarah tidak mempunyai arti apa-apa, boleh jadi karena “tidak bisa jadi nasi” (diá taú jadi bari) yang sangat hedonistik. Terkesan betapa membenci sesama itu lebih gampang dari pada mencintai. Padahal, kebudayaan itu sarinya adalah perdamaian, kemajuan dan saling mencintai.
Sementara, kriteria Trilogi Dayak Ideal ‘Gagah-Berani, Pandai-Berbudi, Kritis-Tekun” (Mamut-Ménteng, Pintar-Harati, Maméh-Ureh) tidak pernah juga diperbincangkan. Trilogi itu dipisah-pisahkan. Tidak dipandang sebagai satu kesatuan. Yang diutamakan adalah ‘Mamut-Ménteng’ yang menghasilkan dominasi ‘budaya’ kekerasan seperti halnya kekeliruan menjadikan ‘talawang’ (perisai) yang alat perang itu sebagai ikon Dayak di seluruh Kalteng. Dari segi filosofi dan kebudayaan Dayak, yang paling sesuai adalah enggang dan naga. Hanya tentu saja membuat patung enggang dan naga pasti lebih rumit dibandingkan dengan membuat talawang. Apakah ini wujud dari kesukaan pada Jalan Pintas dalam masyarakat Dayak hari ini, sebagai akibat dari keterputusan sejarah dan budaya? Apakah Orang Dayak suka berpikir atau lebih suka pada sikap ‘kambing-tumbur’?
Saya membaca masalah menolak memilih Paslon nomor 03 Ganjar-Mahfud karena adanya faktor Mahfud yang Madura adalah menyangkut masalah cara berpikir dan tingkat pengetahuan yang kemudian mengungkapkan diri pada tindakan. Penolakan itu lebih bersifat emosional, bukan rasional (dalam bahasa Dayak: ‘jatun hurui, atau ‘diá tamé akal’).
Dalam upaya menangani hubungan antara dua etnik ini, saya mencoba menghubungi beberapa pekerja budaya di Madura dan masih menunggu tanggapan mereka. Di konteks ini, saya sangat menghargai pentas bersama musisi Madura-Dayak di Jawa (maaf, saya lupa nama kotanya, barangkali Yogyakarta).
Berpikir secara ‘jatun hurui’ atau ‘diá tamé akal’, lebih mendekati sikap ‘kambing-tumbur’ ini, kalau berani jujur pada diri sendiri—hal penting untuk perubahan maju—berlangsung di berbagai bidang dan sejak lama serta menyubur pada masa Orde Baru yang menumbuhkembangkan ‘budaya’ takut. Berpikir secara ‘jatun hurui atau ‘diá tamé akal’ dan sikap ‘kambing-tumbur’ sebenarnya bukanlah tanda kesukaan berpikir, tapi bentuk kemalasan berpikir.
Untuk mewujudan cita-cita Manggatang Utus, seyogyanya Dayak meninjau ulang cara berpikir mereka. Saya khawatir, kalau kita masih berpikir secara ‘jatun hurui’ atau ‘diá tamé akal’ dan bersikap ‘kambing-tumbur’, jarak kita dengan perkembangan zaman yang melaju kencang (Bhs.Dayak: cinik!) tanpa memperdulikan siapapun, akan makin jauh dan makin jauh.
Terbayang di mata saya keadaan Dayak di Nusantara, Ibu Kota Negara yang sedang dibangun tapi sudah lebih papa dari ‘Betawi’. Jika cara berpikir kita tidak diperiksa ulang dengan keras dan jujur, kepapaan itu akan menjadi-jadi dan menunggu kita di seluruh ruang dan relung kehidupan. Dayak menjadi lumpen di Pulau Kelahirannya: Borneo!
Di sinilah pula, saya melihat arti penting mendesaknya penyelenggaraan Kongres Kebudayaan Kalimantan Tengah yang belum pernah dilangsungkan sejak berdirinya provinsi ini pada tahun 1957. Kongres bisa berusaha menyusun strategi kebudayaan Kalimantan Tengah sehingga menjadi Bétang Bersama bagi semua Uluh Kalteng.***
KERAGAMAN INDONESIA DAN UPAYA MENGHINDARI KONFLIK
Oleh: Reyhan Davin Ardhionova* | Penyunting: Andriani SJ Kusni

Tidak dapat dipungkiri lagi, hampir semua wilayah (termasuk kota) di Indonesia adalah wilayah dengan masyarakat multikultur. Para transmigran tentu lebih jelas motivasinya, yaitu mendapatkan tanah dan pekerjaan yang lebih baik di luar Jawa dan Bali.
Namun, kelompok etnis diaspora yang terdiri dari beberapa kelompok etnis tentu memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Para pendatang tersebut (transmigran, diaspora, dan migrasi lainnya) mau tidak mau harus melakukan kontak budaya dengan masyarakat setempat.
Berdasarkan teori kultur dominan, kelompok etnis tertentu menjadi dominan di wilayah teritorialnya. Beberapa provinsi yang termasuk dalam kategori ini antara lain adalah lima provinsi di Jawa (Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Jawa Barat), Bali, Gorontalo, Kalimantan Selatan, Sumatera Barat, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, dan Nangroe Aceh Darusalam. Sementara, kelompok etnis tertentu menjadi dominan di luar wilayah teritorialnya, untuk kategori ini hanya terjadi di propinsi Lampung, dimana orang Jawa menjadi mayoritas (61,89%) diikuti dengan orang asli Lampung justru menjadi minoritas.
Beberapa etnis memiliki jumlah yang berimbang, dapat dikateorikan lagi menjadi: Perimbangan jumlah etnis dengan jumlah etnis asli lebih besar. Kategori ini kebanyakan berasal dari etnis diaspora seperti Batak, Bugis, Melayu, Minahasa, dan Buton di wilayah teritorialnya.
Selain itu, etnis Banten juga paling banyak jumlahnya meskipun tidak dominan. Beberapa propinsi yang termasuk dalam kategori ini antara lain adalah: Banten, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Jambi, Riau, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Tenggara.
Faktor yang membuat perbedaan-perbedaan itu terutama berasal dari ilmu-ilmu perilaku manusia (Behavioral Sciences) seperti sosiologi, antropologi dan psikologi. Ilmu-ilmu sosial tersebut mempelajari dan menjelaskan kepada kita tentang bagaimana orang-orang berperilaku, mengapa mereka berperilaku demikian, dan apa hubungan antara perilaku manusia dengan lingkungannya. Penyebab tersebut telah menimbulkan banyak konflik di dalam masayarakat.
Akhir-akhir ini di Indonesia sering muncul konflik antar ras dan etnis yang diikuti dengan pelecehan, perusakan, pembakaran, perkelahian, pemerkosaan, dan pembunuhan. Konflik tersebut muncul karena adanya ketidakseimbangan hubungan yang ada dalam masyarakat, baik dalam hubungan sosial, ekonomi, maupun dalam hubungan kekuasaan.
Konflik di atas tidak hanya merugikan kelompok-kelompok masyarakat yang terlibat konflik tetapi juga merugikan masyarakat secara keseluruhan. Kondisi itu dapat menghambat pembangunan nasional yang sedang berlangsung.
Indonesia merupakan salah satu bangsa yang paling plural di dunia dengan lebih dari 500 etnik dan menggunakan lebih dari 250 bahasa. Karenanya, sebagaimana bangsa multietnik lainnya, persoalan-persoalan mengenai pengintegrasian berbagai etnik ke dalam kerangka persatuan nasional selalu menjadi tema penting.
Ironisnya, setelah sekian puluh tahun kemerdekaan, pertikaian antaretnik tetap saja terjadi. Sementara pembauran antaretnik intens berlangsung terutama di daerah-daerah urban, konflik antaretnik terus terjadi. Di satu sisi digalakkan upaya untuk meningkatkan nasionalisme guna mengurangi etnosentrisme, di sisi lain tumbuh subur pemujaan etnik.
Memiliki ratusan etnik dengan budaya berlainan, yang bahkan beberapa di antaranya sangat kontras, potensi ke arah konflik sangatlah besar. Ketika Koentjaraningrat mendefinisikan nilai budaya sebagai suatu rangkaian konsep yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar warga masyarakat mengenai apa yang di anggap penting dan remeh dalam hidup, sehingga berfungsi sebagai pedoman dan pendorong perilaku, yang tidak lain mengenai sikap dan cara berpikir tertentu pada warga masyarakat, sekaligus ia menyatakan inilah masalah terbesar dalam persatuan antaretnik (Koentjaraningrat, 1971).
Nilai budaya inilah yang berperan dalam mengendalikan kehidupan kelompok etnik tertentu, memberi ciri khas pada kebudayaan etnik, dan dijadikan patokan dalam menentukan sikap dan perilaku setiap anggota kelompok etnik. Nilai-nilai budaya yang berbeda pada tiap etnik akan menimbulkan sikap dan cara berpikir yang berbeda pula.
Demikian juga dalam perilaku yang diambil meskipun dalam masalah yang sama. Perbedaan ini potensial menimbulkan konflik terutama pada masalah-masalah yang datang dengan adanya interaksi antaretnik.
Upaya Menghindari Konfilk
Berbagai cara dan upaya agar jangan sampai terjadi konflik sangat penting dilakukan. Misalnya, membuat Rancangan Undang-Undang Penghapusan Diskriminasi etnis dan ras hendaknya tidak hanya memfokuskan perhatian pada diskriminasi seperti yang terjadi pada etnis Papua.
Setiap manusia mempuyai kedudukan yang sama dihadapan Tuhan karena dilahirkan dengan martabat, derajat, hak dan kewajiban yang sama. Pada dasarnya, manusia diciptakan dalam kelompok ras atau etnis yang berbeda-beda yang merupakan hak absolut dan tertinggi dari Tuhan Yang Maha Esa.
Dengan demikian, manusia tidak bisa memilih untuk dilahirkan sebagai bagian dari ras atau etnis tertentu. Adanya perbedaan ras dan etnis tidak berakibat menimbulkan perbedaan hak dan kewajiban antarkelompok, ras, dan etnis dalam masyarakat dan negara.
Selain itu, membangun sikap anti diskriminasi etnis dilakukan oleh pihak sekolah merupakan salah satu langkah penting. Dalam poin bahasan ini adalah bagaimana membangun sikap saling menghargai antaretnis yang dimulai melalui institusi sekolah.
Untuk mendukung langkah-langkah guru dalam membangun sikap anti diskriminasi etnis, peran sekolah juga sangat menentukan. Beberapa langkah penting sebaiknya dilakukan pihak sekolah agar siswa dapat secara langsung belajar meningkatkan sensitifitasnya untuk bersikap menghargai etnis lain di lingkungan sekolah.
Indonesia adalah salah satu negara multikultural terbesar di dunia. Kenyataan ini dapat dilihat dari kondisi sosio-kultural maupun geografis yang begitu beragam dan luas. Keragaman ini diakui atau tidak, akan dapat menimbulkan berbagai persoalan seperti korupsi, kolusi, nepotisme, kemiskinan, kekerasan, perusakan lingkungan, separatisme, dan hilangnya rasa kemanusiaan untuk menghormati hak-hak orang lain, merupakan bentuk nyata sebagai bagian dari multikulturalisme tersebut.
*Reyhan Davin Ardhionova, Milenial Pontianak (https://kabardamai.id/keragaman-indonesia-dan-upaya-menghindari-konflik/)

Halaman Budaya Sahewan Panarung | 17 Maret 2024 | Cerpen Korrie Layun Rampan: HAYAPING
Radar Sampit, Minggu, 17 Maret 2024

Kalau bukan karena Ogay, aku tidak akan sampai ke Hayaping. Pernah kudengar nama itu dari temanku, seorang wartawan tabloid reformasi, tapi aku tak juga mampu tiba semauku di tempat itu. Tapi, Ogay membuat aku terpikat, terutama karena di tempat itu terdapat sebuah gua yang dinamakan Liang Saragi.
“Kata orang gua itu indahsekali,” Ogay merayuku.
“Sayang kalau kita tidak menyempatkan diri datang ke situ.”
Dengan motor sewaan aku diboncengi Ogay menuju Hayaping. Meskipun jalannya agak rusak jika berjalan dari arah Tamiang Layang, tetapi Hayaping memiliki daya tarik yang segera membuat aku menyukai tempat itu. Pasarnya yang menjorok ke arah dalam dan keadaan sekitarnya yang membayangkan sebuah kampung yang khas milik orang Dayak.
Kekhasan itu terlihat dari bentuk rumah, logat bicara, dan terutama babi-babi yang lepas berkeliaran di sekitar rumah dan di sepanjang jalan. Bahkan, Ogay hampir saja menabrak seekor babi dengan sejumlah anaknya yang masih kecil saat kami berdua sudah mendekati belokan menuju pasar. Kebetulan kami memang memilih hari pasar yaitu hari Selasa.
Ingin aku menulis tentang sebuah kampung yang merangkak menuju dunia modern, tetapi pada sisi lain masih memelihara tradisi desa tertinggal dengan pola kehidupan nenek-moyang.
“Itulah sebabnya aku membawamu kemari,” Ogay berargumentasi. “Tanpa melihat dari dekat, kau hanya membuat tulisan dari mimpi.”
“Aku memang tak mau menulis impian,” aku membenarkan Ogay. “Karena itu, aku ikut kau melihat kenyataan.”
Sebenarnya, aku mempunyai pengetahuan yang samar-samar dari Billa, puteri pemilik losmen tempat aku menginap di Tamiang Layang. Kampung ini agak jauh menjorok ke dalam, mirip sebuah kota pedalaman. Selebihnya adalah sebuah pasar yang hanya ramai seminggu sekali dan kondisi kampung yang dipenuhi para wisatawan domestik jika tiba masanya ada acara ijame atau musim liburan sekolah dan anak-anak remaja akan memasuki gua.
Ketika aku menggali sumber-sumber kisah dari berbagai kalangan di Kampung Patung dan Simpang Bingkuang, ada yang mengatakan bahwa Liang Saragi merupakan gua terindah dan terpanjang di dunia.
“Jika saja di dalamnya dipelihara dengan baik dan dibuatkan penerangan sehingga terlihat stalaktit dan stalakmit, gua itu akan mampu menghasilkan devisa,” ujar kepala desa. “Panjang liang dunia itu sungguh menakjubkan. Kata orang sampai ratusan kilometer, bahkan mencapai Kota Tanjung di Kabupaten Tabalong.”
“Tapi, siapa yang pernah masuk ke sana? Melihat keindahan yang tak bertara?” seorang anak muda yang tampak cukup kritis berkata dari atas motor ojeknya. “Kita semua hanya mendengar cerita. Tak ada yang berani membuktikan!”
“Kau sendiri tak berani,” seorang anak muda lain menjawab. “Bagaimana kita tahu keadaan sebenarnya kalau hanya menduga-duga?”
“Cobalah kau yang meneliti,” lelaki pengojek lainnya menimpali. “Mudah-mudahan kau akan menemukan harta atau ular siluman.”
“Kau kok malah menakut-nakuti,” lelaki yang lebih kurus berkata bagaikan pokrol bambu. “Kata orang, di zaman Jepang banyak sekali intan permata milik rakyat yang disembunyikan di dalam gua itu.”
“Nah, bukankah itu harta karun?” kepala desa membesarkan nyali warganya. “Kalian bisa minta jaminan keamanan kepada aparat untuk meneliti liang penghasil devisa. Coba, ajukan proposal …”
Para tukang ojek saling pandang. Mungkin kata proposal dianggap aneh. Apa pula maksudnya? Suatu surat lamaran? Pemberitahuan akan melakukan kerja untuk negara? Atau, suatu permintaan untuk mengelola harta masyarakat?
Kudapat cukup bekal untuk melihat kenyataan sebuah gua yang memberi kegirangan bagi pengunjungnya karena indahnya panorama bawah tanah. Jika Billa hanya memberikan bahan samar-samar, para pengojek menambah dengan sejumlah cerita yang mengundang keingintahuan. Tapi, masih bisa kusauk data-data terjadinya gua dan keindahannya serta data-data sejarah dari pihak parawisata. Bukankah mereka sangat berkepentingan dengan gua sebagi sumber pendapatan pemerintah daerah?
Dengan Ogay, aku jakin dapat membuat perjalanan jadi menyenangkan. Kami sudah siapkan peralatan khusus untuk sebuah gua. Dari penuturan kawanku, Danu, yang sering masuk di gua walet Karang Bolong, kutahu banyak mengenai benda-benda penting untuk seseorang pengarung gua. Bukankah berjalan di bawah tanah kadang menemukan bahaya tak terduga. Bukan saja mungkin menemukan ular berbisa, tapi juga disergap gas beracun yang mematikan. Belum lagi bahaya longsor, kejatuhan batu-batu yang licin, atau tercebur ke dalam telaga yang dingin seperti es. Bisa juga ditemukan sumber air panas yang mendidih dan bisa membuat pengarung terebus bagaikan ayam yang matang di kuali para penjual ayam potong di pasar tradisional.
Hayaping dan Liang Saragi membuat aku dan Ogay lebih menyiapkan mental. Jika hanya ingin berbelanja barang-barang di pasar Selasa, kami berdua tidak perlu membawa perlengkapan yang memadai. Soto Banjar yang enak dapat menjadi pengganjal perut dan goreng pisang khas Pasar Hayaping tentu saja bisa menggoyang lidah. Akan tetapi, kami berdua bukan hanya akan melihat keramaian pasar. Kami lebih memfokuskan diri untuk masuk ke dalam gua yang terkenal dengan segala legenda.
Aku sendiri tidak yakin dengan dongeng. Bukankah dongeng adalah cerita rekaan yang diciptakan seorang ahli sastra tradisional yang biasa mengucapkannya secara lisan? Akan tetapi, aku juga tidak bisa menghapus keyakinan masyarakat sehingga tercipta sebuah mitos mengenai kawasan tertentu. Gua Saragi yang diyakini masyarakat sebagai penjelmaan dari suatu peristiwa, harus pula disiasati dengan cerdas bahwa legenda yang ada pasti ada hubungannya dengan kehadiran masyarakat yang mendukung cerita tersebut.
Menurut beberapa informasi yang aku dapatkan dari masyarakat Hayaping, gua itu bukanlah gua yang angker. Belum ada catatan resmi bahwa gua itu menyimpan gas yang menjadi alat pembunuh. Tidak juga pernah terjadi kematian karena dipatuk ular berbisa. Bahkan, di zaman Jepang, di mana sering terjadi gua-gua dan lubang bawah tanah diceritakan menjadi lubang maut, tidak pernah dikisahkan oleh masyarakat yang mengalami zaman itu. Gua Saragi benar-benar merupakan obyek wisata yang paling aman di dunia.
Tak kuragu untuk masuk ke dalam gua. Ogay yang tiba-tiba jadi begitu antusias menemaniku, seperti melupakan tugasnya yang harus segera pulang ke Jakarta karena masa peliputannya di Tumbang Samba sudah selesai. Bahkan berita-berita menyedihkan dari Sampit dan Palangka Raya telah pula direkamnya dan menjadi berita bersambung yang dimuat media tempatnya bekerja.
Tiga jam sudah kami berdua berjalan di lubang gua yang gelap dan pengap. Bagiku sendiri, pengalaman ini adalah pengalaman pertama menyusup di dalam terowongan alami di perut bumi. Aku memang pernah memasuki terowongan kereta api bawah tanah yang disebut metro di Paris. Pernah juga memasuki lekuk dan liku kereta di dalam terowongan di Tokyo. Akan tetapi, gua yang kumasuki ini bukanlah gua yang dibuat manusia. Batu-batu yang menjadi bagian gua alam itu memang indah. Tak ada tangan manusia yang menatanya. Kepengapan yang menandai kelembapan karena berada pada suatu kedalaman bumi, menciptakan sirkulasi udara yang berbeda jika dibandingkan dengan udara di padang terbuka. Masker dan oksigen yang kami bawa sungguh membantu sebagai penguat keyakinan bahwa kami tidak akan terbencana karena terhirup udara busuk atau gas beracun yang dapat menghilangkan nyawa.
Gerakan kelelawar atau walet kadang membuat kejutan. Akan tetapi, apa yang kemudian teronggok di depan kami terasa lebih dari kejutan. Ketika dua lensa senter kami arahkan ke benda-benda yang ada di depan, mata kami jadi terbelalak. Suatu yang tak pernah terbayangkan, justru benar-benar menjadi kenyataan.
***
Upacara penghargaan itu berlangsung dengan meriah. Aku dan Ogay bolak-balik Jakarta-Tokyo karena penemuan di Gua Saragi. Kami berdua diberikan penghargaan karena menemukan rangka Jenderal Takashi Imamura yang harakiri di Gua Saragi pada akhir Perang Dunia Dua. Tapi, saat upacara sedang berada di puncaknya, kala diadakan di Hayaping, kami dikejutkan oleh datangnya teriakan dari seorang wanita tua yang compang-camping.
“Hentikan pemberian hadiah itu. Hentikan!” suaranya dalam teriakan yang serak. “Rangka itu rangka suami saya. Rangka itu bukan rangka Imanura. Rangka itu rangka suami saya karena kekejaman Jepang !”
Acara hampir saja mulur dan kacau kalau pihak keamanan tidak cepat turun tangan untuk mengamankan wanita tua compang-camping. Apa benar rangka itu suami wanita compang? Bukankah sudah dites forensik di laboratorium canggih milik pemerintah negara adikuasa di Asia? Tapi, bukankah jutaan orang Indonesia pernah hilang selama Perang Dunia Kedua? Dan, di dalamnya Jepang dan Belanda harus bertanggung jawab karena mereka yang menciptakan perang di bumi Nusantara?
“Batalkan pemberian hadiah!” teriak wanita itu. “Batalkan pemberian hadiah! Berikan hadiah kepada ahli waris mereka yang telah menjadi korban perang. Berikan hadiah untuk para wanita yang dijadikan jugun ianfu. Berikan hadiah kepada anak cucu korban Perang Dunia Kedua! Tuan-Tuan, jangan menggelar ketidakadilan dengan cara seolah-olah adil!”
Kurasa berjuta mata arwah memandang tajam bagaikan pisau silet melihat ke arah bungkusan hadiah yang diberikan kepadaku dan Ogay. Bukankah kami hanya iseng, tapi menemukan hadiah yang jumlahnya luar biasa. Siapa yang memberikan hadiah untuk mereka yang menjadi korban kekerasan perang dan kekejaman nafsu manusia?
Ludah tak tertelan di tenggorokanku saat tanganku menyambut bungkusan hadiah yang tampak begitu mewah! Cukupkah nilainya untuk dibagikan kepada seluruh korban?
Sentawar, 27 Juni 2001
Catatan:
Ijame = upacara penguburan abu tulang belulang anggota keluarga
Jugun ianfu = memiliki arti “wanita penghibur para tentara”. Sebenarnya sebutan untuk para wanita penghibur dalam beberapa dokumen resmi tentara Jepang adalah Teishintai, berarti barisan sukarela penyumbang tubuh. Sebagian besar para Jugun Ianfu bukan wanita yang bersedia menghibur tentara Jepang secara sukarela. … Proses perekrutan Jugun Ianfu di wilayah Indonesia dilakukan dengan melibatkan perangkat pemerintahan bentukan pemerintah militer Jepang, mulai dari kepala desa hingga ketua tonarigumi dilibatkan dan diwajibkan untuk merekrut perempuan muda dengan dalih program pengerahan tenaga kerja (Oktorino, 2016: 262). ( https://esi.kemdikbud.go.id/wiki/Jugun_Ianfu)
Dr. Hilmar Farid:
“Sakula Budaya Membuka Jalan bagi Anak-Anak Mengenal Lebih Dekat Kebudayaan”
Sambutan pada Acara Tamat Sakula Budaya Handep Hapakat, Desa Sumur Mas, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, 2 Maret 2024

Salam budaya,
Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat atas berlangsungnya kegiatan Sakula Budaya Handep Hapakat di Desa Sumur Mas, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah.
Saya sudah mendengar banyak cerita tentang kegiatan ini, tapi suatu waktu ingin menyaksikan sendiri dan berinteraksi dengan para penyelenggara maupun peserta kegiatan ini. Semoga diberi jalan pada suatu waktu.
Selaku Direktur Jenderal Kebudayaan yang bertugas melaksanakan amanat konstitusi untuk memajukan kebudayaan, saya tentu menyambut baik Sakula Budaya ini sebagai sebuah tonggak penting. Sakula Budaya ini membuka jalan bagi anak-anak kita untuk mengenal lebih dekat kebudayaan mereka, bukan hanya yang terkait kesenian, tapi juga yang berkaitan dengan kebiasaan hidup kita, seperti sandang dan pangan.
Saya secara khusus ingin menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada para pemrakarsa Sakula Budaya, serta semua pihak yang telah mengambil bagian, mulai dari komunitas kesenian, pemangku adat desa, pemerintah desa, dan rekan-rekan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata baik dari Provinsi Kalimantan Tengah maupun Kabupaten Gunung Mas, yang telah bergotong-royong mewujudkan kegiatan ini dan juga mengawal agar terus bisa berlanjut di masa mendatang.
Sakula Budaya ini juga sejalan dengan semangat Program Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dalam program ini, para penyelenggara pendidikan dan peserta didik bersama-sama menggali sumber belajar dari kebudayaan setempat. Proses belajar-mengajar pun menjadi lebih intim, lebih menyenangkan, dan berakar dalam kebudayaan.
Sekian sambutan ini saya sampaikan, atas perhatian dan partisipasinya, saya ucapkan terima kasih.
Salam budaya.
Hilmar Farid
Direktur Jenderal Kebudayaan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

